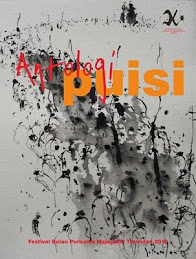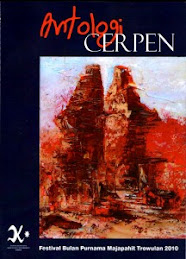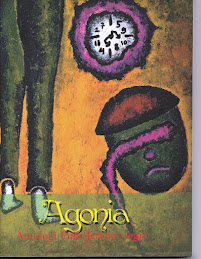Menangisi Nasib Buruh Indonesia
Oleh: Edy Firmansyah
Nasib suram masih menyelimuti kaum buruh Indonesia. Aksi unjuk rasa besar-besaran tiap memperingati hari Buruh Internasional 1 Mei adalah sebuah isyarat bahwa beban kaum buruh kian hari kian berat.
Betapa tidak. Pekerjaan berat yang dijalani kaum buruh tetap saja tidak mampu memenuhi apa yang menjadi standard kebutuhan hidup layak. Buktinya, pemenuhan atas tuntutan upah yang layak, pesangon, cuti hamil, kebebasan berserikat, tunjangan hari raya dan berbagai hak normatif lainnya masih sebatas wacana. Benar memang wacana tersebut hingga saat ini masih terus diperjuangkan. Tapi resiko dari perjuangan tersebut juga tidak kecil. Yakni, resiko pemutusan hubungan kerja secara sepihak dari perusahaan dimana mereka bekerja.
Akibatnya bisa ditebak, kaum buruh tetap berkubang dalam lumpur kemiskinan. Benar memang jika berpegang pada ukuran garis kemiskinan BPS tahun 2005 yang sekitar Rp 135.000/kapita/ bulan, buruh Indonesia dengan upah rata-rata Rp 700.000-Rp 800.000 sekarang ini memang tidak termasuk miskin.
Namun, karena setiap buruh menanggung rata-rata empat anggota keluarga (termasuk dirinya sendiri), kalaupun tidak di bawah garis kemiskinan, mereka tetap miskin. Belum lagi ditambah dengan melambungnya harga kebutuhan pokok. Makanya jangan heran jika buruh hidup di perkampungan kumuh dengan standar kesehatan di bawah rata-rata, dengan anak-anak putus sekolah adalah fenomena biasa. Hal tersebut dilakukan hanya untuk menyeimbangkan antara pendapatan yang minim dengan biaya kebutuhan hidup yang kian melambung tinggi.
Padahal buruh-lah tulang punggung setiap laju industri di belahan dunia manapun. Silahkan para pengusaha memiliki bergunung-gunung emas. Tapi tanpa kerja para buruh, emas tersebut tak akan ada artinya. Sebab melalui tangan buruhlah emas itu akan dapat berlipat ganda. Nah, semestinya kaum buruh mendapatkan penghasilan yang layak berdasarkan kerjanya. Artinya gaji yang mereka terima lebih besar dari gaji tenaga ahli atau mandor perusahaan yang bisanya hanya menunjuk saja.
Tapi sayang hal itu tak pernah terjadi. Buruh masih terkungkung dalam keharusan bertahan hidup dengan upah minimum ditengah melonjaknya harga kebutuhan pokok. Inilah yang disebut Marx sebagai sebuah alienasi. Buruh tak lagi mampu mengembangkan diri. Kesempatan belajar, kesempatan untuk menikmati keindahan alam dan budaya, keindahan untuk menikmati filsafat dan spiritual musnah oleh upaya-upaya survival (Kusumandaru, 2003).
Alienasi inilah sebenarnya yang menjadi penyebab rendahnya kualitas kerja buruh. Bagaimana mungkin mereka meningkatkan wawasan, pengetahuan dan intelektual mereka sebagai modal aplikatif dalam kerjanya sementara untuk membeli buku saja mereka tidak sanggup?
Buruh dalam Cengkraman Politik
Pemerintah sebenarnya tahu betul kehidupan miskin kaum buruh. Pemerintah juga telah mengambil beberapa langkah untuk menaikkan derajat hidup kaum buruh. Salah satunya dengan rencana mereformasi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun sayangnya, langkah pemerintah justru mengarah pada keberpihakan pada investor atau pemilik modal. Akibatnya rencana melakukan perombakan terhadap UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut kembali mendapat protes dari para buruh.(Kompas, 2/5/2007)
Pasalnya, reformasi kebijakan ketenagaankerjaan dikhawatirkan akan melahirkan pasar kerja yang fleksibel (labour market flexibility). Kondisi ini jelas-jelas semakin menguatkan posisi pengusaha dalam mengembangkan modal dengan biaya produksi dan upah murah. Sedangkan hak-hak kaum buruh kian rentan. Pertama, Sebab pemilik modal dengan mudah mengontrol dan mendepak tenaga kerja melalui skema kerja kontrak (outsourcing) tersebut. Dengan sistem ini tidak ada pilihan lain bagi kaum buruh untuk terus menghamba pada pemilik modal. Mereka harus pasrah bongkokan dengan pemberian upah murah
Kedua, kebebasan berpikir dan berpendapat melalui unjuk rasa dan demo lambat laun akan mati. sebab buruh dihadapkan pada posisi yang sangat dilematis. Jika melakukan demo hanya untuk menuntut kenaikan upah, pengusaha tidak akan segan-segan memutuskan kontrak. Itu berarti dapur tidak ngepul. Sebaliknya, jika buruh diam saja atas perlakukan sewenang-wenang pemilik modal, berarti penguasa akan semakin ’liar’ mengambil kebijakan yang menyengsarakan para buruh.
Itulah yang disebut Johnson Panjaitan dan sejumlah ahli perburuhan, sebagai politik buruh murah. Awalnya politik ini diterapkan pemerintah Orde Baru, demi kepentingan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Tapi karena dirasa cukup efektif politik tersebut masih diterapkan penguasa negeri ini hingga sekarang.
Untuk kepentingan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, buruh yang tidak berdaya menjadi korban yang paling mudah ditindas, untuk mencapai efisiensi atau daya saing perusahaan. Upah buruh murah juga menjadi jualan untuk menarik investasi asing ke sektor manufaktur di Indonesia. Hal serupa terjadi pada buruh tani atau petani yang menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang menempatkan sektor pertanian tak lebih sebagai pengganjal atau pelengkap bagi sektor industri dan sektor modern lain di perkotaan.
Dan nampaknya cara semacam itu cukup berhasil. Buktinya, berdasarkan data yang dihimpun Sri Hartati Samhadi (Kompas, 2005), angka kasus mogok memang jauh menurun dalam beberapa tahun terakhir, dari 174 kasus (tahun 2001), menjadi 220 kasus (2002), 161 kasus (2003), dan 112 kasus (2004). Demikian pula angka kehilangan jam kerja, menurun dari 1.165,032 jam sepanjang tahun 2001, menjadi 769.142 jam (2002), 648.253 jam (2003), dan 497.780 jam (2004). Namun dibandingkan negara lain, tinggi.
Siapa lagi yang diuntungkan dengan nasib buruh yang kian hari kian tertekan? Siapa lagi kalau bukan kaum politisi. Sebab jumlah buruh cukup banyak dan sangat berpotensi mendulang suara dalam pemilihan umum. Dari sekitar 95 juta tenaga kerja yang bekerja tahun 2005, sebesar 70,22 juta orang masuk kategori pekerja kerah biru, sementara 24,73 juta orang pekerja kerah putih (mengandalkan kemampuan intelektual untuk mencari nafkah).
Karenanya tidak heran jika isu buruh sering hanya dijadikan sebagai kendaraan politik untuk mengantarkan elit politik ke tampuk kekuasaan. Terlebih lagi ketika menjelang pemilu dan pilkada. Partai politik berserta elitnya ramai berkotbah di mana-mana, mengobral janji dengan mengatasnamakan dan memperjuangkan nasib buruh. Tapi begitu kekuasan diraih, buruh kembali dieksploitasi.
Di hadapan para politisi dan partai politik yang pragmatis, buruh lebih banyak diomongkan ketimbang diperjuangkan. Lihat saja, hingga saat ini nasib buruh tidak kunjung berubah. Kian hari hidup mereka kian digilas roda pembangunan dan globalisasi. Tak ada sekolah murah bagi anak buruh. Selain itu, mereka tak punya jaminan atas kesehatan. Benar memang kini telah ada askeskin. Tapi rumah sakit tetap saja mengutamakan pelayanan prima bagi pasien yang berduit.
Membangun Kemandirian
Jika kondisi itu dibiarkan maka buruh akan terus menjadi obyek penderita dalam setiap laju produksi. Karena itu perlu dibangun kemandirian dalam internal buruh sendiri. Menggantungkan harapan pada solusi-solusi pemerintah bisa dibilang keputusan yang sia-sia. Kemandirian tersebut tentu saja dalam arti politik. Bahwa kaum buruh perlu membangun jaringan besar yang menjangkau semua pekerja di seluruh pabrik di negeri ini. Pasalnya, perlawanan buruh secara sektarian atau secara otonom terbukti tidak cukup berhasil menaikkan derajat hidup buruh. Semakin besar jaringan buruh yang dibangun, maka semakin kuat daya tawar kaum buruh terhadap penguasa dan pengusaha. Nasib buruh yang tragis bisa dijadikan isu bersama untuk menyatukan perjuangan buruh. Bahkan jika memungkinkan bergandengan tangan dengan partai-partai progresif yang serius memperjuangkan nasib buruh juga perlu dilakukan.
Sebenarnya nasib buruh tak terus mengalami keterpurukan seandainya pemerintah mau mengambil kebijakan yang prorakyat seperti yang dilakukan Bolivia atau Venezuela. Kedua negara amerika Latin itu dengan cukup berani melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing. Kemudian pengelolaannya diserahkan pada para buruh. Sehingga pengaturan upah dilihat dengan seberapa berat beban kerja, bukan dengan seberapa banyak saham yang ditanam.
Tapi Apa boleh buat? Kesejahteraan buruh di negeri ini memang tak akan diberikan cuma-cuma, selama berada ditangan para penguasa korup dan pemilik modal bebal. Bahkan meski keuntungan yang mereka peroleh sudah setinggi gunung. Karenanya Kaum buruh harus merapatkan barisan.***
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Peneliti pada IRSOD (Institute of Reaseach Social Politic and Democracy) Jakarta. Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember. Ketua FORDEM (Forum Demokrasi) Pamekasan-Madura.