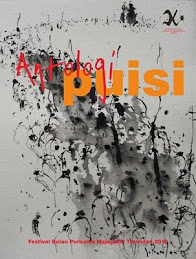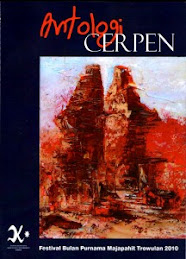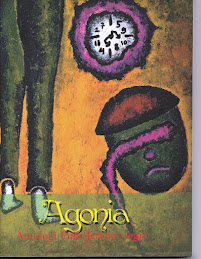Dimuat di WACANA, SUARA MERDEKA, 12 Agustus 2008
Merdeka Dengan Membaca
Oleh: Edy Firmansyah Barangkali
Barangkali para pendiri negeri ini bakal kecewa jika hakekat dan tujuan proklamasi kemerdekaan 63 tahun lalu hanya dimaknai dengan kesuksesan membangun gedung pencakar langit, mal, plasa, sementara disparitas kemiskinan terus membengkak. Mungkin pula mereka sedang berduka menyaksikan anak cucu bangsa yang lebih suka menghabiskan waktu menonton televisi dan jalan-jalan di mal ketimbang membaca buku.
Padahal, republik ini didirikan supaya anak cucu bangsa bisa terus mengembangkan diri, berkreasi dan melakukan inovasi sebagai modal kemandirian bangsa. Karena saat tidak lagi dikhawatirkan serangan senapa dan bom tiba-tiba. Yang dikhawatirkan adalah serbuan globalisasi yang bisa menjadikan masyarakat negeri ini tergantung pada negeri lain. Melawan ketergantungan dengan kemandirian, kreativitas dan inovasi hanya bisa terwujud jika masyarakat negeri ini adalah masyarakat yang rakus membaca.
Sayangnya hal tersebut tidak terjadi. Meski banyak masyarakat kita yang sudah dapat membaca, namun ternyata belum mampu membaca secara benar, yakni membaca untuk memberi makna dalam meningkatkan nilai kehidupannya.
Masyarakat kita adalah masyarakat yang membaca hanya untuk mencari alamat, membaca untuk mengetahui harga-harga, membaca untuk melihat lowongan pekerjaan, membaca untuk menengok hasil pertandingan sepak bola, membaca karena ingin tahu berapa persen discount obral di pusat perbelanjaan dan akhirnya membaca sub-title opera sabun di televisi untuk mendapatkan sekedar hiburan (Ajidarma; 2005;133).
Makanya jangan heran jika kualitas sumber daya manusia (SDM) kita masih masih jauh tertinggal dengan negara lain. Kita lebih senang menjadi bebek (baca: mengekor) daripada menjadi trendsetter. Itu karena wawasan pengetahuan kita amat rendah untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru yang memajukan peradaban.
Padahal kalau kita mau menilik sejarah awal kebangkitan bangsa ini, minat baca masyarakat kita ternyata tidak separah yang kita bayangkan sekarang. Pada awal kebangkitan nasional minat baca masyarakat juga tak kalah menakjubkan. Douwes Dekker mencatat setidaknya ada 34 majalah terbitan bangsa Indonesia. Dan pada tahun 1923, ketika diadakan survei terhadap ”pers pribumi Hindia Belanda” ternyata jumlah majalah meningkat jadi 107 macam! Bisa dibayangkan betapa tinggi minat baca dan hasrat menulis bangsa kita waktu itu.
Makanya jangan heran generasi era 45 adalah generasi pilih tanding. Betapa tidak, karena kekuatan imajinasinya yang diperoleh dari berbagai bacaan mereka akhirnya mampu merumuskan secarik kertas proklamasi yang menjadi tonggak berdirinya negeri ini.
Sikap Paradoks
Memberikan pendidikan yang layak bagi setiap warga negaranya adalah tugas pemerintah. Gerakan ini keaksaraan dan pengembangan literasi yang dimotori oleh beberapa elemen masyarakat, tentu akan jauh lebih efektif jika gerakan ini juga didukung penuh oleh pemerintah. Kader-kader baca tentu akan lebih leluasa melakukan pendampingan dan pendidikan literasi pada masyarakat. Terlebih lagi jika didukung dengan kebijakan yang sangat pro literasi.
Tapi hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, sikap pemerintah seringkali paradoks dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat. Benar memang pemerintah gencar melakukan program pemberantasan buta aksara. pemerintah juga kerap memasang slogan-slogan di berbagai pusat keramaian dan sudut kota untuk menumbuhkan minat baca seperti: Budayakan membaca buku, Buku adalah jendela dunia, Biasakan memberi hadiah buku, dan lain sebagainya. Tapi dorongan untuk menumbuhkan minat baca tersebut seringkali kontradiktif.
Mau bukti? pemerintah telah memangkas anggaran untuk perpustakaan sebagai dampak dari pemotongan anggaran pendidikan sebesar 10 persen. Akibatnya, bantuan rintisan dan penguatan taman bacaan masyarakat sebesar sektiar Rp. 41 miliar di 33 proponsi dengan target awal sekitar 2.250 lembaga terancam batal. Sedangkan pengadaan sebanyak 143 taman bacaan masyarakat layanan khusus bersifat mobile tidak jadi dilaksanakan lantaran anggarannya yang sebesar Rp 46 miliar terpangkas seluruhnya. (Kompas, 21/0408).
Padahal perpustakaan adalah jantung ilmu pengetahuan. Sejarah telah membuktikan betapa perpustakaan mampu melahirkan orang-orang besar. Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Gusdur, tak akan mungkin memiliki pemikiran brilian yang mampu memberikan perspektif baru dalam kemajuan bangsa jika tidak ditunjang oleh buku-buku. Bahkan Eka Budianta, salah seorang budayawan Indonesia, dari kecil sudah biasa nangkring di perpustakaan umum Kota Madya Malang, meskipun harus bersepeda 5 kilometer.
Tapi yang terjadi di negeri ini justru kebalikan dari semua itu. Bukan rahasia umum kalau perpustakaan umum dan daerah yang sudah ada justru tak terurus dan terkesan diterlantarkan. Koleksi bukunya sudah usang, tempat penyimpanan tidak representatif dan nyaris tidak ditemukan buku-buku baru. Toh, meskipun ada buku baru, biasanya buku dengan sampul dan isinya masih mulus (karena tak tersentuh) tapi terbitan lama. Pengunjung setianya pun bisa dihitung dengan jari.
Karena itu satu-satu jalan melejitkan kemampuan SDM manusia secara maksimal adalah pemerintah harus proaktif dan terlibat penuh dalam kerja-kerja literasi. Negara Jepang sudah membuktikan betapa dasyatnya kekuatan buku. Setelah gagal dalam Perang Dunia II dan porakporanda dihantam bom atom AS, Jepang mulai membangun kembali negerinya dengan membaca.
Mereka mulai memasukkan ratusan bahkan ribuan buku dari luar Jepang, menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang, lalu mulai menganjurkan masyarakatnya untuk terus dan terus membaca. Hasilnya luar biasa. Hanya dalam waktu kurang dari 30 tahun, Jepang mampu bangkit. Bahkan kemudian mengimbangi kemajuan Amerika Serikat dan banyak negara maju lainnya dalam membangun ekonomi dan teknologi. Saya yakin semua elemen negeri ini tak mau terus-terusan menjadi bangsa benalu. Karena itu, tidak ada kata lain untuk membangkitkan lagi ghiroh kemerdekaan, selain membangkitkan semangat membaca masyarakat.
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Pengelola Sanggar Bermain Kata (SBK) Madura. Peneliti pada IRSOD (Institute of Reaseach Social Politic and Democracy), Jakarta. Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.
 Dimuat di Media Indonesia, 30 Agustus 2008
Dimuat di Media Indonesia, 30 Agustus 2008