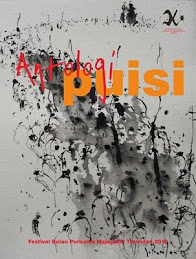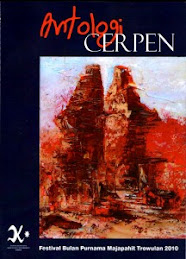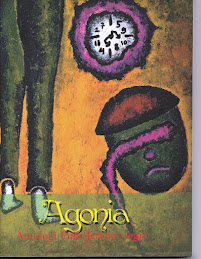SEDIKIT BENTO DALAM KONG
Sejak pertamakali diproduksi Hollywood pada tahun 1933, film King Kong
garapan Merian C. Cooper dan Ernest B. Schoedsack segera menarik
perhatian. Tidak hanya bagi penonton, tetapi juga bagi industri layar
lebar dengan laba yang dihasilkan dari pemutaran filmnya. Makanya tak
heran jika film dengan tokoh monyet raksasa itu sempat memiliki sejumlah
sekuel sekaligus diulangbuat beberapa kali. Taruhlah misalnya, King
Kong garapan John Guillermin pada tahun 1976 silam Dan King Kong garapan
Peter Jackson yang dirilis 2005.
Dua film dengan tokoh monyet
raksasa yang disebut di atas itu memiliki alur cerita yang sama dengan
film tahun 1993. Seekor monyet raksasa penguasa pulau Skull Island jatuh
cinta pada seorang aktris bernama Ann Darrow (tahun 1933 diperankan Fay
Way, tahun 1976 diperankan Jessica Lange dan tahun 2005 diperankan
Naomi Watts) yang sedang menghadapi maut ketika hendak dipersembahkan
pada si monyet sebagai tumbal oleh penduduk setempat. Dari situlah
ketegangan-ketegangan dimulai. Yach mirip-mirip kisah Beauty and the
Beast milik Disney.
Nah, tahun 2017 ini Jordan Vogt-Roberts kembali
mencoba membuat ulang film Kong itu. Dengan efek yang lebih bagus dan
alur cerita yang berbeda. Berbeda? Iya, dengan naskah cerita yang
digarap bersama oleh Dan Gilroy (Nightcrawler, 2014), Max Borenstein
(Godzilla, 2014) dan Derek Connolly (Jurassic Park, 2015).
Hasilnya, tidak
ada lagi monyet raksasa yang jatuh cinta pada perempuan. Yang ada
adalah Kong si penjaga pulau. Pelindung kehidupan hutan. Si mahkluk
raksasa penjaga harmoni alam. Perhatian Kong pada karakter Mason Weaver
hanya sebuah tribut pada konflik klasik di film King Kong terdahulu.
Bukan cerita utamanya.
Juga tidak ada lagi penduduk primitif
yang buas dan jahat, yang ada adalah penduduk hutan yang ramah dan
melindungi dan memuja Kong sebagai dewa, bukan sebagai monster yang
meminta tumbal manusia secara berkala. Tidak ada lagi plot kapal besar
yang ditumpangi sutradara gagal dan aktris gagal yang mencoba membuat
film di pulau asing. Tak ada lagi adegan membawa Kong ke kota untuk
dipertontonkan pada manusia modern.
Kali ini yang hadir dalam
Kong garapan Jordan Vogt-Roberts adalah sekelompok pasukan helikopter
yang dipimpin Lieutenant Colonel Preston Packard (Samuel L. Jackson) dan
seorang mantan pasukan elit militer Inggris, Captain James Conrad (Tom
Hiddleston). keduanya dipekerjakan oleh agen pemerintah Bill Randa (John
Goodman) untuk mengawal ekspedisinya dalam memetakan sebuah pulau asing
di Samudera Pasifik yang selama ini dikenal sebagai Skull Island.
Perjalanan itu juga diikuti oleh jurnalis foto, Mason Weaver (Brie
Larson), yang mencurigai bahwa ekspedisi ilmu pengetahuan tersebut
hanyalah sebuah samaran bagi sebuah operasi militer rahasia yang sedang
dijalankan pemerintah. Setibanya di Skull Island, pasukan helikopter
yang dibawa Bill Randa mulai menjatuhkan rentetan bom yang digunakan
untuk mengetahui kondisi tanah di pulau tersebut. Tanpa disangka, satu
sosok monyet raksasa penghuni Skull Island yang merasa terganggu atas
kedatangan kelompok tersebut lantas melakukan serangan mematikan.
Menyerang dan menghancurkan helikopter. Tindakan tersebut tidak lagi
sebuah tindakan membabi buta, melainkan upaya melindungi pulau dari
kebangkitan kull Crawler – seekor kadal raksasa yang dikisahkan pernah
membunuh keluarga Kong dan menjadi musuh utama bagi para penghuni Skull
Island.
Mau tak mau Captain James Conrad dan kawanannya yang
selamat dari serangan pertama, harus bertahan hidup di pulau tersebut
sebelum pasukan penyelamat datang tiga hari kemudian.
Pada
menit-menit pertama, saat menonton Kong: Skull Island garapan Jordan
Vogt Roberts, saat lagu The Hollies--band pop rock asal Inggris era
60an--mengalun, kontan saya berteriak dalam hati: Bento nih. Bento.
Pasalnya, instrumen lagu berjudul Long Cool Woman in a Black Dress itu
mirip banget dengan instrumen musik salah satu lagu Iwan Fals yang
terkenal itu. Bento.
Memang Vogt-Roberts sepertinya sengaja
memasukkan deretan lagu-lagu rock popular di tahun ‘70an ke dalam banyak
adegan film penuh makhluk gigantis itu. tapi serasa tidak terlalu
mengesankan jika dibandingkan dengan soundtrack, misalnya, Guardians of
the Galaxy (James Gunn, 2014) yang sukses menjadikan setiap lagu klasik
dalam adegan filmnya sebagai pendukung suasana pengisahan atau Soundtrack film Dead Poll, deretan lagu
dalam jalinan kisah Kong: Skull Island terasa hambar.
Namun efek
visualnya patut dijempol. Dengan sentuhan efek visual sekaligus
dukungan penampilan motion capture dari aktor Terry Notary yang
memerankannya, penampilan Kong tampak sangat meyakinkan. Konon ukuran
Kong dibikin Jauh lebih besar dari Kong milik Peter Jackson. Kera
berukuran gigantis itu digambarkan memiliki tinggi 100 kaki. Di tangan
sutradara film drama The King of Summer ini, Kong bahkan memiliki
kepribadian yang jauh lebih berwarna dari kebanyakan karakter manusia
yang mengisi jalan cerita film. Dengan lain kata, film Kong: Skull
Island seakan hendak menggiring penonton justru agar fokus pada karakter
Kong dan kehidupan yang berada di sekitarnya. Hutan, pulau dan
ekosistem alam di dalamnya. Sehingga seakan-akan karakter-karakter
manusia dalam jalan penceritaan film ini menjadi sama sekali “tidak
berguna” kehadirannya.
Pertempuran Kong dengan kadal raksasa yang
bringas dan buas adalah fokus utama film ini. Kita akan disuguhkan efek
pertarungan raksasa baik melawan raksasa jahat. Manusia hanya cukup
menonton dan menyelamatkan diri. Pertarungan hidup mati pada paruh akhir
penceritaan Kong: Skull Island menghadirkan puncak ketegangan maksimal
bagi jalan cerita film dan mampu tereksekusi dengan sangat baik.
Akibatnya, seakan tak satupun diantara karakter tersebut yang memiliki
pendalaman kisah yang cukup berarti. Kebanyakan diantara mereka malah
hanya dihadirkan sebagai korban keganasan raksasa-raksasa penghuni Skull
Island dengan deretan dialog yang cukup menggelikan. Para
tentara-tentara yang kalah perang dalam perang Vietnam jadi terlihat
makin konyol. Kecuali karakter Hank Marlow yang diperankan oleh John C.
Reilly dan digambarkan sebagai sosok mantan anggota pasukan militer
Amerika Serikat yang telah terdampar di Skull Island selama 28 tahun
memiliki deretan kisah yang membuat karakternya begitu menarik. Begitu
pula dengan karakter Lieutenant Colonel Preston Packard yang diperankan
Jackson. Terutama saat dia berteriak: “aku ajarkan padanya kali ini raja
diraja bumi ini adalah manusia”. Angkuh di tengah kerapuhannya pada
maut. Meskipun hadir terlalu terbatas, karakteristik antagonis itu
mampu diterjemahkan dengan baik.
Namun, lepas dari semua itu,
Kong: Skull Island berhasil meyakinkan saya bahwa memang manusia itu
cuma elemen kecil dalam semesta. maka tidak pantaslah menjadi perusak
alih-alih demi nasionalisme. Menonton Kong: Skull Island, saya
terbayang-bayang begitu banyaknya penolakan penduduk adat dan hutan pada
eksploitasi alam atas nama tambang. Seakan-akan penolakan itu seperti
raksasa yang bangkit melindungi harmoni alam. Dan akan terus membesar.
Seperti Kong.