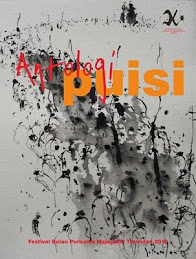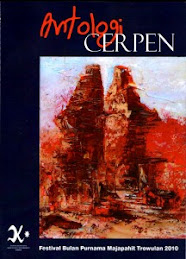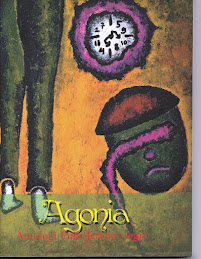" Cerita Tentang Sebuah Ledakan"
ada yang meledak di udara
ada yang meledak
orang orang menutup mata
lalu mendongak ke angkasa
jalanan runtuh, gedung-gedung melepuh
orang orang melihat tuhan dari lubang sedotan yang jauh
seorang kepala negara mencungkil sepasang matanya
lalu jumpa pers dimulai;
"tak ada yang perlu ditakutkan. kemiskinan menurun dalam angka statisitik"
dia berbohong. dia berbohong.
di luar istana jutaan orang saban hari kelaparan.
di luar istana jutaan orang tidur di kandang hewan
"percayalah kita aman. kita aman. kita bangsa besar yang berdaulat"
sekali lagi dia berbohong. dia berbohong
ketakutan ditebarkan negara tiap hari
emas, perak dan nikel dijarah di Papua
minyak dan batubara dijarah di Sumatera
jutaan masyarakat hutan kehilangan tanahnya
belatung belatung terus keluar dari matanya yang berlubang
bau busuk menyebar ke penjuru kota
ada yang meledak lagi di udara
ada yang meledak
sepertinya kita harus belajar menutup telinga
atas segala kebohongan yang ditularkan media
kita juga harus belajar mengakhiri semua dengan mata terpejam
dan melihat dengan hati murka
Madura, 2005-2013
WAKTU
JEJAK
- Artikel (93)
- Cerpen (20)
- Esai Budaya (31)
- Jendela Rumah (24)
- Kesehatan Masyarakat (5)
- Pendidikan (10)
- PUISI (71)
- Resensi Buku (25)
JEDA
Kamis, 19 Juni 2014
" Cerita Tentang Sebuah Ledakan"
Label:
PUISI
Selasa, 10 Juni 2014
Musim Coblosan!
Siapapun presidennya, minumnya tetap darah rakyat! ~ Tono, tukang tambal ban
“Tentukan pilihan presidenmu sekarang! Atau kau akan menyesal karena menjadi bagian dari para pengacau dan pecundang.” Kalimat itu pertama kali saya baca dari status BBm seorang teman. Ketika membaca itu sejenak saya tertegun. Segenting itukah? Sesakral itukah pemilu yang sebentar lagi akan digelar? Sejahat itukah golput hingga dituding para pengacau plus pecundang?
“Tentukan pilihan presidenmu sekarang! Atau kau akan menyesal karena menjadi bagian dari para pengacau dan pecundang.” Kalimat itu pertama kali saya baca dari status BBm seorang teman. Ketika membaca itu sejenak saya tertegun. Segenting itukah? Sesakral itukah pemilu yang sebentar lagi akan digelar? Sejahat itukah golput hingga dituding para pengacau plus pecundang?
Beberapa hari lalu saya membaca berita tentang dua tukang becak yang berkelahi hanya karena saling ejek soal capres. Suto dan Saleh nama kedua tukang becak itu. Keduanya biasa mangkal di simpang empat Jalan Kemuning, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan. Suto adalah pendukung capres Jokowi-Jusuf Kalla, sementara Saleh adalah pendukung Prabowo-Hatta Rajasa. Perkelahian itu diawali dengan saling hujat capres masing-masing.
Berita itu begitu mudah menyebar karena momentumnya tepat. Menjelang pemilu. Sepintas memang menjelang pemilu keadaan genting. Dukung mendukung membuat orang saling membenci dan berkelahi. Tapi benarkah? Tiba-tiba saya teringat perkataan Malcom X; “Jika kamu tidak peduli, koran akan membuatmu membenci orang-orang yang sedang tertindas, dan mencintai orang-orang yang melakukan penindasan”
Kelas menengah mungkin akan menertawai ‘kegoblokan’ dua tukang becak itu. Kita mencibirnya di fesbuk dan twitter. Menertawainya sebagai kekonyolan. Tanpa pernah mau peduli apakah berita itu hanya dibuat untuk membenarkan opini bahwa tiap pemilu suasana politik selalu panas. Berita rumah terbakarpun bahkan jika dibumbui karena pemiliknya lalai karena sedang berdebat dengan tetangga lainnya soal capres bisa jadi headline. Dan makin sempurnalah penderitaan tukang becak itu. Kere, berkelahi karena urusan sepele (capres). Diberitakan. Kemudian dicibir seantero jagad nusantara. Menyenangkan ya!? Yang memberitakan puas. Entah menipu atau kenyataan tak ada yang tahu. Yang membaca berita puas. Kesemuanya memenuhi selera pasar masyarakat Indonesia yang suka menertawai yang tertindas lewat acara reality show. Klop.
Selang beberapa hari setelah ramai berita tukang becak berkelahi itu, debat capres cawapres digelar. Tidak di jalanan. Tapi di gedung megah. Tidak ada adu jotos seperti berita tukang becak tadi. Hanya ada argumen laiknya seorang intelektual gedongan. Usai acara itu dinding fesbuk saya ramai memberi skor hasil debat. Ramai mengomentasi tiap detail jawaban para capres-wapres yang diusungnya. Sesekali nyentil pendukung capres saingannya. Saya tidak menonton. Saya memilih tidur. Karena saya memang tak berminat dengan debat itu. Barangkali jika ada debat capres melawan golput saya akan meluangkan waktu untuk menontongnya. Kapan ya? Entahlah.
Lalu apa hubungannya tukang becak berkelahi dengan debat capres di gedung sarbini? Kita diberi kesan bahwa kelas menengah kita yang intelektual itu cocok untuk memimpin negeri ini. Siapapun pemimpinnya. Terimalah dengan tangan terbuka siapapun pemenangnya. Jangan lagi berharap pada perjuangan kelas dan kekuatan buruh dan proletariat karena mereka tidak pernah siap menghadapi kenyataan demokrasi ini. Mereka kasar. Gampang berkelahi di jalanan. Media seakan hendak membentuk opini masyarakat agar sama sekali tidak mempercayai kelas buruh. Kesan ini mengingatkan saya pada penyataan teman saya di status BBmnya. “Memilih netral atas nama rasa marah, kecewa atau berdasarkan ideologi dan keyakinan politik apapun sama sekali berbahaya. Ada yang mengancam di ujung sana. Sebuah bahaya; kembalinya rejim militeristik di Indonesia” begitu urainya.
Kawan “kiri’ saya itu seakan-akan hendak berkata bahwa tidak ada pilihan lain. Untuk membendung gelombang datangnya militerisme di Indonesia kita harus berpihak, mendukung salah satu calon yang lebih progresif. Meskipun (dengan kalimat yang berat) liberal dan kapitalistik.
Berpihak pada salah satu diantara dua capres yang ada? Saya berpikir keras. Kawan saya itu sedang bicara politik atas kepentingan dirinya sendiri atau rakyat? Saya menduga banyak kelas menengah berbicara pemilu dan mendukung salah satu calon capres atas nama rakyat cuma sebuah pelarian untuk melanggengkan kenyamanan ekonomi yang telah ia nikmati sepanjang tahun hidupnya meski telah berganti-ganti kepala negara. Jangan-jangan olok-olok dan caci maki antar pendukung capres yg berlaga saat ini di berbagai sosial media yang hiruk-pikuknya kadang melebihi supporter bola hanya sebuah ilusi untuk menutupi kenyataan bahwa di luar gadget mereka ada pertarungan kelas yang tengah terjadi. Pertarungan yang begitu keras sekaligus sunyi. Ah..semoga dugaan saya salah dan cuma imajinasi di sela-sela berpikir tadi. Diantara upaya saya berpikir itu, tiba-tiba melintas bayangan poster-poster kampanye yang masih menampilkan muka-muka lama dengan wajah belepotan darah rakyat dan dosa masa lalu dan tak kunjung “diberi ganjaran sesuai rasa keadilan.” Di poster-poster itu tersenyum para pelanggar HAM, pembuat “bencana” nasional, menteri penjilat atasan, dan hal lainnya membikin rasa kemanusiaan pengen mencret rasanya.
Mereka para capres dan pendukungnya itu semua boleh teriak anti korupsi, sekencang-kencangnya. Sekeras-kerasnya. Pakek toa masjid se antero nusantara jugak nggak apa-apa. Suka-suka merekalah. Tapi jika partai pengusungnya belum berani transparan soal dana kampanye itu namanya lawakan demokrasi. Lawakan transparansi. Bukankah lumrah kalau kontes presiden maupun anggota legislatif pasti ada saweran dari luar? Ya certain dong sejujur-jujurnya atas nama transparansi yang diucapkan mulut dan lidahnya sendiri itu.
Tapi nyatanya kontes presiden dan anggota legislatif, meski banyak yang ingin tahu sumber dana kampanyenya, justru rapat tertutup. Singit-singitan. Sembunyi di balik mulut-mulut lapar menganga. Masa sih cuma dari patungan anggota partai? Dan pemberi saweran itu tentu bukan tanpa pamrih kan? Hari gini gitu loh, mana ada yang gratis sih? Berak di terminal saja bayar! Tak perlu normatif lah, serba lumrah kok.
Belum lagi cerita-cerita kecurangan sepanjang pesta demokrasi. Ada cerita satu desa tidak mencoblos karena surat suara sudah dihendel kepala desa. Jadi kepala desa dan kroni-kroninya yang mencoblos. Cerita tentang suara yang hilang saat penghitungan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Meski cerita-cerita itu telah banyak masyarakat liat sendiri dengan mata kepalanya sendiri, entah mengapa mereka masih rela berduyun-duyun ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), meninggalkan pekerjaannya yang penting cuma untuk berpanas-panas dalam antrian, mirip kelas menengah ibukota menyambut gadget baru dengan harga diskonan. Merepotkan. Padahal dengan makin maraknya hape, khan cukup memilih lewat sms. Lebih murah, lebih hemat. Toh upaya kecurangannya bisa lebih canggih. Toh sama-sama curang tho. Toh juga hasil akhirnya cuma voting.
Dan yang paling ironis dalam pesta demokrasi bernama pemilu ini, rakyat memilih cuma lima menit untuk lima tahun. Bahwa setelah lima menit pengambilan suara itu, rakyat tak lagi bisa bersuara untuk lima tahun ke depan, karena telah diambil suaranya. Rakyat, kata yang akhir-akhir ini begitu keramat bahkan oleh para pembencinya sendiri, harus menunggu lima tahun untuk bisa menggunakan suaranya lagi. Kalaupun bisa menggunakan suaranya sebelum lima tahun, itupun harus melalui demo dan aksi jalanan yang kadang malah mendapat cibiran dan cacian. Paling parah dipentungi dan ditembaki aparat. Sementara mereka yang dipilih untuk menentukan “nasib bangsa” kualitasnya masih serba entah. Serba hitam. serba gelap. Makanya menyebarlah kampanye hitam di mana-mana. Oya, satu lagi. Tak ada pula kartu garansi. Pemenang kontes lima tahunan ini tak disertai kartu garansi, tak bisa di-recall kembali jika mengecewakan. Padahal lima tahun bukan waktu yang pendek.
Jadi siapapun presidennya rakyat akan tetap menghadapi ancaman. Kesehatan mahal, pendidikan mahal, pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, upah murah di mana-mana. Anak putus sekolah di mana-mana. Pengusiran masyarakat adat demi eksploitasi tambang di mana-mana. Penggusuran pemukiman miskin (setelah digusur dibangun mall dan hotel mentereng). Sebab sistem ekonomi yang diterapkan masihlah sistem ekonomi kapitalistik. Kunjungan para capres kepada para tani dan buruh hanyalah untuk mencari simpatik. Ujungnya untuk mendulang suara dari tani dan buruh. Tapi tak akan pernah memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan tani dan buruh.
Tapi benarkah tidak ada pilihan lain? Cuma ABG unyu-unyu yang menganggap setelah demokrasi pemilu semua jalan hanya jalan buntu. Tak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Negara cuma alat. Demokrasi pemilu cuma alat melanggengkan mereka yang berkuasa atas Negara. Karena cuma alat, harusnya tak perlu terlalu unyu-unyu dengan negara. Seperti hp, kalau negara rusak, ya diperbaiki. Kalau tak bisa diperbaiki lagi, ganti baru saja, gitu aja kok repot. Yang merasa repot dan kebakaran jembut kan yang berkepentingan, penguasa, pemodal dan mereka yang sudah pernah menikmati nyamannya jadi penguasa atau yang nyaman berdiri di kaki kekuasaan yang bakal bernasib sial bakal ikut diganti kalo negara diganti. Rakyat mana bisa diganti? Memangnya mau diganti pakai apa? Tiang bendera?
Karenanya yang dibutuhkan hari-hari ini adalah penguatan basis gerakan kaum buruh dan tani. Tak perlu ikut hiruk pikuk pemilu yang cuma sekedar reality show kaum penguasa. Jalan politik bukan cuma pemilu saja. Semua yang menyangkut kekuasaan dan hajat hidup orang banyak adalah tindakan politik Sementara penguasa kapitalistik negeri ini tak bisa menjamin roti dan perdamaian yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya tanpa memandang kelas. Namun tak ada jalan pintas untuk mengubah keadaan. Apalagi hanya dengan melompat-lompat partai. Perlu mentalitas dan kedisiplinan tingkat akut untuk menguatkan gerakan. Tanpa kekuatan basis gerakan progresif, buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota akan kehilangan momentum revolusinya. Dan makin gampang dicabik-cabik kaum penguasa kala mereka sudah kehilangan akal menghadapi kebuntuan-kebuntuan ekonomi dengan melepas gerombolan anjing gilanya.
Ingatlah selalu. Waktu begitu pendek. Dan mereka yang menyesal adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu. Selamat memilih! Saya memilih piknik!
Langganan:
Postingan (Atom)