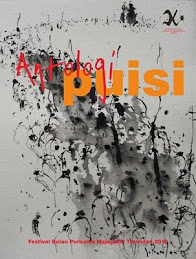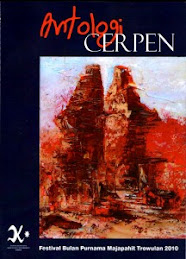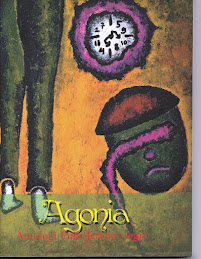Dimuat di Harian Umum PELITA, 25 dan 27 November 2008
Oleh: Edy Firmansyah  Menurut Daniel Bell, salah seorang sosiolog posmodern, masyarakat Instan adalah masyarakat yang menanggalkan sikap sabarnya. Tak mau lagi percaya bahwa peradaban manusia yang paling maju dilalui melalui proses panjang yang pembelajaran tanpa henti. Masyarakat instan, lanjut Bell, masyarakat yang mati nurani dan akal budinya. Yang dikedepankan adalah kepentingan parsial, dan percaya satu-satunya keinginan dan asanya bisa dicapai dengan uang.
Menurut Daniel Bell, salah seorang sosiolog posmodern, masyarakat Instan adalah masyarakat yang menanggalkan sikap sabarnya. Tak mau lagi percaya bahwa peradaban manusia yang paling maju dilalui melalui proses panjang yang pembelajaran tanpa henti. Masyarakat instan, lanjut Bell, masyarakat yang mati nurani dan akal budinya. Yang dikedepankan adalah kepentingan parsial, dan percaya satu-satunya keinginan dan asanya bisa dicapai dengan uang.
Pandangan Daniel Bell diatas nampaknya cukup relevan bagi masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat Indonesia yang dikenal pekerja keras dan gigih meraih cita-cita kini berubah menjadi masyarakat yang serba instan. Maraknya kasus ingin kaya instant dengan korupsi, jual beli ijasah instan, bisnis gelar instan (entah oleh institusi atau oknum beberapa Perguruan Tinggi ) merupakan buktinya.
Kapitalisme dengan mesin giling produksinya telah menyeret kita dalam sekrup-sekrup produksi sehingga kita lahir menjadi manusia yang seragam, yang tunduk pada kaidah pasar. Mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya hingga pendidikan. Dalam dunia pendidikan, misalnya mata pelajaran dicacah menjadi kepingan pengetahuan yang berujung pangkal pada hubungan jual beli yang sarat dengan kaidah individualistik. Dengan kata lain, pendidikan bukan lagi pengetahuan yang mengasah humanisme untuk kemaslahatan umat.
Makanya jangan heran jika praktek jual beli ijasah instan semakin marak dilakukan. Temuan maraknya ijasah di Surabaya sebenarnya merupakan puncak dari gunung es praktek jual beli ijasah instan. Maklum, masyarakat kita terbiasa silau dengan gelar akademik. Semakin tinggi gelar yang disandang seseorang, maka akan semakin terangkat pula status sosialnya. Karenanya ijasah yang kerap menjadi incaran masyarakat gila gelar ini terutama ijasah sarjana, pasca sarjana dan doktor seperti; Drs, Dr, MA, MEd, MSi, MM, dan seterusnya. Lihat saja, di instansi pemerintahan. Banyak pejabat yang menyandang gelar akademik tinggi. Bahkan sampai tingkat doktor.
maraknya ijasah di Surabaya sebenarnya merupakan puncak dari gunung es praktek jual beli ijasah instan. Maklum, masyarakat kita terbiasa silau dengan gelar akademik. Semakin tinggi gelar yang disandang seseorang, maka akan semakin terangkat pula status sosialnya. Karenanya ijasah yang kerap menjadi incaran masyarakat gila gelar ini terutama ijasah sarjana, pasca sarjana dan doktor seperti; Drs, Dr, MA, MEd, MSi, MM, dan seterusnya. Lihat saja, di instansi pemerintahan. Banyak pejabat yang menyandang gelar akademik tinggi. Bahkan sampai tingkat doktor.
Bagaimana kualitasnya? Sungguh menyakitkan dunia pendidikan. Sebab diantara para Magister dan doktor itu kebanyakan tak bisa menuliskan pemikirannya ke media massa atau membuat penelitian bertaraf nasional. Dengan lain kata, logika dan retorika mereka stagnan. Mereka merasa cukup bangga dengan titel tinggi tapi memiliki kemampuan jongkok.
Tak heran jika negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini justru terpuruk karena Human Development Index (HDI) berada di urutan paling buncit diantara Negara dunia ketiga,. Merupakan negeri terkorup, salah satu negeri penghutang terbanyak, serta negeri yang berada tepat di depan jurang krisis ekonomi. Dan hal ini salah satunya disebabkan banyak masyarakatnya yang hanya sekedar menjadi intelektual instan. Cukup menyandang gelar kesarjanaan, meski hasil membeli.
Padahal, menurut D.J Drost (2005:80) ciri khas calon intelektual Indonesia yang matang adalah fasih dalam menguasai bahasa Indonesia, baik saat bertutur maupun saat menulis. tata bahasa dan ejaan harus dikuasai secara mutlak. Logika bahasa mencirikan segala cara berkomunikasi. Logika bernalar dan bertutur diperoleh dan dibentuk selama mengenyam pendidikan, terutama lewat matematika dan bahasa Indonesia.
Matematika mengajar kita berpikir Logis. Namun karena matematika adalah ilmu kuantitas, perlu juga ditunjang pengetahuan yang lain. Seperti misalnya bahasa asing. Hanya saja yang paling menunjang dan memperluas perolehan lewat matematika adalah bahasa. Seseorang baru bisa bernalar dan bertutur dewasa baik dengan lisan maupun tulisan bisa sudah menguasai ortografi, gramatika dan sintaksis bahasanya sendiri.
Di samping itu, penting juga untuk menguasai tekhnologi. Karena dengan tekhnologi mereka dapat memperoleh informasi dengan mudah. Dengan begitu para intelektual akan mampu mengembangkan wawasannya. Sayang itu tak pernah terjadi di negeri ini. Bahkan para penyandang gelar S1, S2 atau S3 instan yang kini duduk di jajaran pejabar pemerintahan atau pendidik ada pula yang tidak dapat mengoperasikan Komputer. Apalagi Internet.  Yang jadi pertanyaan untuk apa menyandang gelar tinggi tapi tidak mumpuni secara dalam pengetahuan? Apalagi jika bukan untuk mempertahankan siklus feodalistik. Mempertahankan klas borjuasinya. Seperti mendapatkan kedudukan yang tinggi di birokrasi. Setelah kedudukan telah diraihnya, korupsi akan dijadikan pilihan untuk mengembalikan modal setelah dihabiskan untuk meraih gelar instan itu.
Yang jadi pertanyaan untuk apa menyandang gelar tinggi tapi tidak mumpuni secara dalam pengetahuan? Apalagi jika bukan untuk mempertahankan siklus feodalistik. Mempertahankan klas borjuasinya. Seperti mendapatkan kedudukan yang tinggi di birokrasi. Setelah kedudukan telah diraihnya, korupsi akan dijadikan pilihan untuk mengembalikan modal setelah dihabiskan untuk meraih gelar instan itu.
Kondisi diatas berbeda jauh dengan kondisi di negara-negara maju. Belum pernah Margaret Teacher memasang gelar Dra. Maupun MA. Apalagi Mikhail Gorbachev S.H!Bahkan untuk ilmuwan-ilmuwan penting, penggunaan gelar itu juga tidak lazim. Tidak pernah kita mendengar Prof. Dr. Charles Darwin, atau Prof. Albert Einstein PhD.(Eka Budianta, 1993;137-138). Ya. Di negara maju ukuran kemampuan seseorang bukan karena gelar yang disandangnya. Melainkan karya yang dihasilkannya. Meskipun tak pernah mengenyam pendidikan tetapi mampu menciptakan pembaharuan, mereka akan dihormati.
Karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk mengakhiri semua fenomena yang melecehkan dunia pendidikan ini. Tidak cukup dengan menindak tegas oknum pelakunya saja. Kedepan harus segera dilakukan perombakan sistem pendidikan. Dari pendidikan yang bertujuan sekedar mencetak lulusan sebanyak-banyaknya, menjadi pendidikan yang melejitkan kualitas peserta didiknya. Dan mengembalikan pendidikan sebagai jalan pengangkatan manusia muda ke taraf insani sehingga ia dapat menjalankan hidupnya sebagai manusia utuh, tangguh dan membudayakan diri. Pendidikan sebagai proses hominisasi dan humanisasi membantu manusia muda untuk berkembang menjadi manusia, bermoral, bersosial, berwatak, berpribadi, berpengetahuan dan beruhani. Artinya lulusan sekolah, terutama para sarjana tidak hanya fasih berteori, tetapi mampu bertahan hidup dan mengembangkan diri bahkan di tengah badai krisis sekalipun.
Jujur saja negeri ini tak akan pernah maju dan masyarakatnya tidak akan pernah sejahtera jika dipegang oleh intelektual yang berangkat dan melambungkan namanya melalui kepalsuan. Yang terjadi justru korupsi dan penindasan yang kian menyakitkan.***
Tentang Penulis
WAKTU
JEJAK
- Artikel (93)
- Cerpen (20)
- Esai Budaya (31)
- Jendela Rumah (24)
- Kesehatan Masyarakat (5)
- Pendidikan (10)
- PUISI (71)
- Resensi Buku (25)
JEDA
Jumat, 28 November 2008
Masyarakat Instan dan Intelektual Karbitan
Deforestasi dan Peta Penanggulangan Banjir
Dimuat di harian RADAR SURABAYA, 24 November 2008
Deforestasi dan Peta Penanggulangan Banjir
Oleh: Edy Firmansyah Musim hujan kembali tiba. Masyarakat Jawa Timur mulai diliputi rasa rasa getir, waswas, dan khawatir. Kekhawatiran masyarakat Jawa Timur sangat beralasan. Pasalnya, pada musim penghujan tahun 2007 lalu, setidaknya ada 14 wilayah di Jatim yang terkena banjir dan tanah longsor. Wilayah tersebut diantaranya; Surabaya , Sidoarjo, Jember, Situbondo, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, dan Tuban.
Musim hujan kembali tiba. Masyarakat Jawa Timur mulai diliputi rasa rasa getir, waswas, dan khawatir. Kekhawatiran masyarakat Jawa Timur sangat beralasan. Pasalnya, pada musim penghujan tahun 2007 lalu, setidaknya ada 14 wilayah di Jatim yang terkena banjir dan tanah longsor. Wilayah tersebut diantaranya; Surabaya , Sidoarjo, Jember, Situbondo, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, dan Tuban.
Akibat bencana tersebut, pemukiman penduduk, sawah, fasilitas sosial, rumah sakit, sekolah di wilayah tersebut tenggelam. Ribuan penduduk terisolasi dan kelaparan. Jalur transportasi juga lumpuh total. Kerugian nyaris tak terkirakan. Bayangkan saja, dalam hitungan kasar kerugian akibat banjir di 15 Kecamatan di Bojonegoro mencapai Rp 93,3 miliar. Kerusakan sawah dan tambak di Tuban mencapai Rp, 25,6 miliar.
Tentu saja sejarah kelam diatas tidak ingin terulang lagi. Hanya saja sepertinya alam belum mau bersahabat dengan kita. Buktinya, meski menurut ramalan BMG curah hujan masih normal, beberapa di Jawa Timur sudah dilanda banjir dan longsor.
Benar memang musim penghujan tahun ini pemerintah tidak tinggal diam. Beberapa persiapan mengantisipasi bencana akibat musim penghujan telah dilakukan. Pemerintah Kabupaten Lamongan misalnya, sudah mengaktifkan satuan pelaksana penanggulangan bencana. Mulai mengeruk embung dan waduk-waduk desa. Juga telah dibangun bendung gerak untuk mengendalikan banjir. Sementara itu pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga telah memperbaiki lima titik tanggul. (Kompas Jatim, 17/11/08)
Memang tidak ada yang keliru dari usaha pemerintah mengantisipasi bencana banjir. Hanya saja pemerintah belum pernah memikirkan untuk memperluas hutan di wilayahnya. Padahal berdasarkan data yang disimpan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) sejak tahun 1945 hingga masa reformasi tahun 1997 telah terjadi deforestasi sebanyak puluhan juta hektar. Di Sumetera, pada tahun 1945 luas hutannya mencapai sekitar 48 juta hektar, tetapi pada tahun 1997 tinggal 18 juta hektar. Di Sulawesi, luas hutan pada tahun 1945 sekitar 20 juta hektar. Namun pada 1997 justru menjadi 10 juta hektar. Di Jawa tak jauh beda. Jika pada tahun 1945 hutan di Jawa mencapai 10 juta hektar, pada tahun 1997 justru menyusut 10 juta hektar. Jadi kini tinggal 2 juta hektar saja.
pemerintah belum pernah memikirkan untuk memperluas hutan di wilayahnya. Padahal berdasarkan data yang disimpan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) sejak tahun 1945 hingga masa reformasi tahun 1997 telah terjadi deforestasi sebanyak puluhan juta hektar. Di Sumetera, pada tahun 1945 luas hutannya mencapai sekitar 48 juta hektar, tetapi pada tahun 1997 tinggal 18 juta hektar. Di Sulawesi, luas hutan pada tahun 1945 sekitar 20 juta hektar. Namun pada 1997 justru menjadi 10 juta hektar. Di Jawa tak jauh beda. Jika pada tahun 1945 hutan di Jawa mencapai 10 juta hektar, pada tahun 1997 justru menyusut 10 juta hektar. Jadi kini tinggal 2 juta hektar saja.
Bahkan tak menutup kemungkinan angka deforestasi tersebut saat ini meningkat tajam mengingat pola pembangunan kita yang nyaris tidak pro-lingkungan (baca: hutan). Banyak hutan kita dibakar dengan sengaja karena ingin mendirikan pabrik, bangunan kapitalisme, dan lahan ekonomis. Pemegang HPH dan elite pemerintah yang berkepentingan dengan hutan sengaja menyewa orang guna membakar hutan di daerahnya dengan orientasi akumulasi surplus. Seperti membangun villa atau membangun ladang kelapa sawit demi kepentingan profit. Lemahnya aparat penegak hukum kita untuk menangkap dan memenjarakan para pembakar hutan, lenjarah hutan, penebang pohon dan semakin mempertegas deforetasi hutan kita. Dibebaskannnya Adelin Lis adalah salah satu contohnya.
Padahal hutan merupakan metode paling efektif mencegah banjir dan longsor. Berapapun derasnya air hujan yang jatuh tak perlu ditakutkan dan dikhawatirkan masyarakat. Karena hutan yang rimbun (yang berisi banyak pepohonan besar) masih mampu menampung air hujan berapapun volume air hujan yang jatuh pada suatu wilayah. Karenanya tak keliru jika Vandana Shiva, salah seorang aktivis lingkungan dan tokoh ekofeminisme India mengatakan; “Peluklah pohon kita, selamatkan mereka dari penebangan. Jaga hutan kita, maka hutan-hutan itu akan menyelamatkan kita.”
Hal berikutnya yang luput dari perhatian pemerintah soal antisipasi bencana adalah masih dijalankannya ’represi struktural.’ Represi struktural, dapat dirasakan pada kemunculan hegemoni bahasa, dimana hanya pejabat yang berkuasa yang berhak memberikan tafsiran atas realitas yang terjadi dalam masyarakat. Artinya, hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan bencana banjir dan memberi solusinya.
Padahal selama berabad-abad lalu manusia memiliki sistem pertahanan hidup sendiri untuk dapat survive di daerah yang didiaminya. Mereka yang hidup menjadi bagian dari ekosistem sebuah wilayah telah mengenal betul lingkungan mereka degan baik. Analisa rasional mereka sangat bermanfaat demi kelangsungan hidup. Masyarakat di pesisir pantai misalnya, hanya dengan melihat gelombang laut dan perubahan rasi bintang sudah mampu memprediksi bakal terjadi tsunami besar. Tapi ilmu pengetahuan yang turun temurun itu lambat laun di’hancurkan.’ Anak petani, nelayan dan permabah hutan sudah tidak lagi mengenal itu semua, karena disekolah tak satupun ada pelajaran mempertahankan hidup terhadap alam. Untuk apa? Apalagi kalau bukan untuk menjauhkan mereka dari lingkungan hidupnya sehingga mudah terserap dalam kerja-kerja kasar sebagai buruh murah.
Karena itu, mengembalikan pengetahuan lokal masyarakat saat ini merupakan keniscayaan. Masyarakat harus kembali dibekali dengan ilmu pengetahun dan prediksi-prediksi alamiah mengenai gejala alam. Hal ini penting agar bencana dapat semakin mudah diantisipasi. Bukankah jika masyarakat pandai dan menguasai teknik-teknik analisa klimatologi (bahkan yang paling dasar) justru semakin memperingan beban pemerintah dalam mengantisipasi bencana?
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Peneliti pada IRSOD ( Institute of Reasearch Social Politic and Democracy). Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.
Rabu, 26 November 2008
Waria Juga Manusia Biasa
Dimuat di Harian SURYA, 20 November 2008
Waria Juga Manusia Biasa
Oleh: Edy Firmansyah Tak banyak yang tahu jika tanggal 20 November diperingati sebagai hari Transgender/Waria Internasional. Maklum selain peringatan tersebut baru memasuki tahun ke sembilan, ternyata masih sedikit masyarakat yang menaruh simpati pada para transgender ini. Buktinya, aksi-aksi kaum waria tiap tanggal 20 November dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka sebagai manusia justru dianggap angin lalu, bahkan disikapi sinis banyak kalangan masyarakat.
Tak banyak yang tahu jika tanggal 20 November diperingati sebagai hari Transgender/Waria Internasional. Maklum selain peringatan tersebut baru memasuki tahun ke sembilan, ternyata masih sedikit masyarakat yang menaruh simpati pada para transgender ini. Buktinya, aksi-aksi kaum waria tiap tanggal 20 November dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka sebagai manusia justru dianggap angin lalu, bahkan disikapi sinis banyak kalangan masyarakat.
Padahal para transgender ini amat rentan mengalami diskriminasi dan tindak kekerasan. Mereka masih kerap menjadi korban kekerasan dan pembunuhan, baik oleh perorangan, aparat hukum ataupun kelompok yang antiwaria atas dasar kebencian dan prasangka buruk. Salah satu peristiwa yang menjadi tonggak diperigatinya hari transgender ini adalah terbunuhnya seorang waria bernama Rita Hester di San Fransisco pada tahun 1998. Kasus tersebut tidak pernah terselesaikan hingga kini. Artinya, korban-korban lain yang senasib dengan Rita Hester kemungkinan besar terus bertambah. Barangkali razia Sat Pol PP terhadap para waria yang disertai dengan tindak kekerasan seperti menyeret, menjambak, mencemooh bahkan mencaci para waria adalah fenomena gunung es diskriminasi dan kekerasan terhadap para waria.
Sebenarnya apa yang membuat kaum transgender ini terus mengalami diskriminasi baik secara sosial, budaya, pendidikan dan politik? Menurut Foucault dalam Power/Knowledge pelabelan atas penyimpangan seksual direproduksi oleh rezim yang sedang menguasai, mengorganisisr, merumuskan dan mengkategorisasi makna. Artinya, apa yang disebut sebagai penyimpangan seksual merupakan bentuk hegemoni bahasa, dimana hanya yang berkuasalah yang berhak memberikan stigma normal atau tidak normal dalam sebuah komunitas masyarakat.
Transgender sebagai the minor term (baca: kelas pinggiran) tidak dikonstruksikan untuk keberadaan dan kepentingan kaum waria sendiri, namun justru untuk kepentingan kaum heteroseksual sebagai penyandang the major term. Secara politis para transgender/waria ini justru dianggap sebagai sebuah kegagalan the minor term dalam upaya menyesuaikan diri dengan identitas gender (feminin-maskulin) dab seksual (laki-laki – perempuan) yang telah terstruktur jelas di Indonesia. Kegagalan itulah yang kemudian digembar-gemborkan para pemegang kuasa makna melalui corong-corongnya (media, kebijakan dan sebagainya) sebagai acuan masyarakat untuk menolak mereka sebagai “warga negara yang baik” dan “normal” (Alimi dalam Kadir, 2007;80-81).
keberadaan dan kepentingan kaum waria sendiri, namun justru untuk kepentingan kaum heteroseksual sebagai penyandang the major term. Secara politis para transgender/waria ini justru dianggap sebagai sebuah kegagalan the minor term dalam upaya menyesuaikan diri dengan identitas gender (feminin-maskulin) dab seksual (laki-laki – perempuan) yang telah terstruktur jelas di Indonesia. Kegagalan itulah yang kemudian digembar-gemborkan para pemegang kuasa makna melalui corong-corongnya (media, kebijakan dan sebagainya) sebagai acuan masyarakat untuk menolak mereka sebagai “warga negara yang baik” dan “normal” (Alimi dalam Kadir, 2007;80-81).
Padahal kalau kita membaca beberapa babakan sejarah di Nusantara, dapat kita lihat betapa kaum transgender dulunya merupakan bagian dari komunitas masyarakat. Mereka bisa hidup berdampingan baik dengan masyarakat kelas bawah maupun masyarakat kelas atas. Artinya, fenomena transgender tidak muncul secara temporer di stasiun-stasiun kereta api, salon-salon, para desainer mode kelas menengah, penata rambut, peraga dan sejenisnya.
Dalam penelitiannya Benedict Anderson menyebutkan kaum bangsawan Aceh sering membeli laki-laki kemayu dari Nias (Seudati) untuk dijadikan “kesenangan” di ranjang maupun disuruh menari dengan berpakaian wanita. Bahkan nalam naskah Jawa kuno kehidupan waria terpampang jelas pada serat Centhini. Dalam naskah tersebut dikisahkan mengenai Nurwitri dan Cebolang yang diperlakukan sebagai pihak feminin ketika mereka bertemu dengan adipati di Kabupaten Daha.  Bahkan pengakuan terhadap transgender ini sudah pernah dilakukan Nabi Muhammad ketika menetap di Medinah. Kaum laki-laki yang tidak mempunyai hasrat terhadap perempuan ini biasa disebut mukhanath yakni mereka yang menetap di luar nilai-nilai seksual patriarki pada waktu itu dan bergaya layaknya perempuan. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad menerima keberadaan mereka selama tidak merugikan tata nilai etis tertentu. (Al Haqq Kugle dalam Kadir, 2004;88). Artinya, bahkan Nabi Muhammad-pun telah mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia, karena manusia sejatinya sama dihadapan tuhan.
Bahkan pengakuan terhadap transgender ini sudah pernah dilakukan Nabi Muhammad ketika menetap di Medinah. Kaum laki-laki yang tidak mempunyai hasrat terhadap perempuan ini biasa disebut mukhanath yakni mereka yang menetap di luar nilai-nilai seksual patriarki pada waktu itu dan bergaya layaknya perempuan. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad menerima keberadaan mereka selama tidak merugikan tata nilai etis tertentu. (Al Haqq Kugle dalam Kadir, 2004;88). Artinya, bahkan Nabi Muhammad-pun telah mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia, karena manusia sejatinya sama dihadapan tuhan.
Sayangnya agama dan negara justru hendak mengingkari sejarah keberadaan para transgender. Susahnya para transgender ini mengurus KTP (terutama berkenaan dengan jenis kelamin), hingga keinginan untuk membina rumah tangga dengan kaum laki-laki. Bahkan kaum agamawan kerap menuding-nuding orientasi seks menyimpang yang justru menjadi penyebab krisis multidimensi di negeri ini. Padahal masalah tak akan pernah selesaiseberapapun kerasnya negara dan agama menekan para transgender. Mereka akan terus ada, karena mereka merupakan bagian dari peradaban manusia. Tindakan represif semacam itu justru malah akan menimbulkan perlawanan dan jika hal tersebut terjadi justru semakin memperumit keadaan. Saya yakin para pemegang kekuasaan tak menginginkan itu terjadi bukan? 
Karena itu memberikan hak penuh bagi para transgender sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pilihan bijak. Memberikan kesempatan bagi para transgender untuk berkativitas dibidang politik, sosial, budaya, pendidikan dengan damai dan tentram ditengah-tengah para heteroseksual adalah keputusan paling manusiawi. Sebab waria juga manusia, punya hati punya rasa. Masalahnya bagaimana dengan kita? Adakah hati dan rasa kita untuk mereka?
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Jurnalis. Peneliti pada IRSOD (Institute of Reasearch Social Politic and Democracy).
Selasa, 25 November 2008
Peta Penanggulangan Kemiskinan
Dimuat di Harian PELITA, 20 November 2008
Peta Penanggulangan Kemiskinan
Oleh: Edy Firmansyah Kemiskinan di negeri ini masih dalam kondisi memprihatinkan. Hingga Juni 2007, angka kemiskinan masih berada pada angka 37,17 juta atau 17,75 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dan angka ini relatif belum banyak berubah dari angka tahun 2005.
Kemiskinan di negeri ini masih dalam kondisi memprihatinkan. Hingga Juni 2007, angka kemiskinan masih berada pada angka 37,17 juta atau 17,75 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dan angka ini relatif belum banyak berubah dari angka tahun 2005.
Bahkan angka diatas kemungkinan besar meningkat drastis pasca kenaikan BBM sebesar 26, 8 persen beberapa waktu lalu. Dengan kenaikan BBM harga seluruh komoditas (yang sebelumnya telah merambat naik) menjadi semakin tak terjangkau melonjak. Akibatnya transaksi antarkota, antar propinsi dan antarpulau dipastikan turun drastis, bahkan berhenti total. Sebab harga barang dagangan tak akan mampu bersaing karena harus menyesuaikan dengan biaya transportasi yang juga akan naik.
Dengan kondisi tersebut jelas banyak usaha yang gulung tikar. Sehingga PHK pekerja menjadi peristiwa yang tak terelakkan. Angka pengangguran juga melonjak drastis. Imbasnya tentu saja jumlah masyarakat miskin akan semakin meningkat. Berdasarkan perkiraan Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi, kenaikan harga BBM sebesar 30 persen berpotensi mengakibatkan orang miskin bertambah sebesar 8,55 persen atau sekitar 15, juta jiwa.
Jika kondisi diatas dibiarkan maka malapetaka akibat kemiskinan sebagaimana diramalkan Susan George dalam bukunya The Lugano Report: On Preserving Capitalism in Twenty-first Century (1999;2003), ada di depan mata. Menurut Susan George kemiskinan yang terus meningkat akan menghasilkan jutaan masyarakat kelas bawah yang tidak lagi memiliki tempat di pemukiman kota dan di dalam ekologi. Kondisi ini bukan hanya dapat meningkatkan intensitas konflik, kriminalitas dan anarkisme dalam masyarakat, melainkan juga menciptakan kerusakan lingkungan.
Gejalanya sepertinya sudah mulai terasa. Diperkotaan tindakan kriminal, tawuran, pembunuhan terus meningkat tajam. Sementara di pedalaman kita saksikan sekitar 10 juta warga miskin kita yang mencari apapun, termasuk membabat hutan demi mendapat makan. Karena tuntutan perut mereka merusak lingkungan. Untuk hal ini, masyarakat miskin memang tidak bisa dipersalahkan begitu saja. Masalah kemiskinan adalah masalah negara. Sebagaiamana termaktup dalam UUD bahwa orang miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Masalahnya adalah sudahkah upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan optimal??
Kalau merujuk pada Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan yang diadopsi menjadi Bab 16 dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 kita dapat membaca metode kemiskinan dengan metode participatory poverty assesment (PPA) sesuai harapan banyak organisasi non pemerintah. Metode tersebut sebenarnya merupakan upaya mengembalikan analisa kemiskinan pada ’fitrah’nya. Yakni membaca kemiskinan dengan narasi-narasi kualitatif yang tak lazim dipakai kaum tekno-ekonom. Sehingga penanggulangan kemiskinan bergerak berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan merujuk pada budaya lokalnya dan kemampuan orang miskin menentukan kebijakan ekonomi politiknya sendiri, bukan upaya penanggulangan kemiskinan hanya sekedar menurunkan angka statistik.
Sayang, dokumen itu tidak dijadikan road map penanggulangan kemiskinan. Dokumen itu menjadi tak ada artinya saat negara (dalam hal ini konspirasi legislatif-eksekutif) memproduksi legislasi kebijakan makro-ekonomi yang berkiblat pada pasar dan investasi (baca;neoliberalisme), sesuai dengan petuah lembaga multilateral dan donor multilateral yang menjadi sumber utang pendanaan pembangunan.
Salah satu kebijakan yang sebenarnya anti pemberdayaan kemiskinan adalah digulirkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekitar 3 Trilyun rupiah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Dapat kita saksikan berbondong masyarakat mendaftarkan diri menjadi pengemis. Kita saksikan kaum miskin dan orang-orang yang pura-pura miskin rela antre sembari ‘menengadahkan tangan’ sebagai pesakitan guna mendapatkan talangan dana dari pemerintah. Padahal cara semacam itu tak pernah mampu membebaskan masyarakat miskin dari lubang hitam kemiskinan. Yang terjadi justru ketergantungan masyarakat miskin pada dana bantuan. Dan ini menyebabkan mereka malas dan enggan bekerja keras memperbaiki nasib.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekitar 3 Trilyun rupiah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Dapat kita saksikan berbondong masyarakat mendaftarkan diri menjadi pengemis. Kita saksikan kaum miskin dan orang-orang yang pura-pura miskin rela antre sembari ‘menengadahkan tangan’ sebagai pesakitan guna mendapatkan talangan dana dari pemerintah. Padahal cara semacam itu tak pernah mampu membebaskan masyarakat miskin dari lubang hitam kemiskinan. Yang terjadi justru ketergantungan masyarakat miskin pada dana bantuan. Dan ini menyebabkan mereka malas dan enggan bekerja keras memperbaiki nasib.
Benar memang ada program pemerintah yang digulirkan dengan mengusung platform pemberdayaan masyarakat seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Namun program tersebut belum sepenuhnya membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Program ini cukup berhasil dalam membuka akses sosial ekonomi masyarakat seperti pembangunan jalan dan jembatan (juga sekolah). Tapi masyarakat tak pernah tahu atau diberi tahu bagaimana menjawab kemiskinan yang obyektif. Sehingga infrastruktur yang dibangun tak ubahnya monumen penanggulangan kemiskinan belaka. Disamping itu, dana dari program ini masih menjadi bancaan para birokrat, para kepala desa, dan fasilitator program.  Padahal kita tahu masyarakat miskin adalah masyarakat paling gigih dalam survive melawan krisis. Lihatlah para PKL. Digusur ribuan kali mereka terus berjualan dengan segala cara dan motif. Justru ditengah keterjepitan dan ancaman hidup mereka memeras otak agar bisa terus makan. Termasuk makan nasi aking atau pelepah pisang. Dengan semangat hidup itu sebenarnya mereka memiliki potensi untuk bangkit dari kemiskinannya. Tinggal bagaimana pemerintah yang bekerja sama dengan ornop pro masyarakat miskin dan partai progresif melakukan pendampingan untuk mengubah nasib mereka baik secara ekonomi maupun politik. Karena itu agenda mendesak dalam penanggulangan kemiskinan adalah melepaskan diri dari cengraman neoliberalisme dan menyusun kembali strategi kemiskinan sesuai kondisi riil masyarakat.
Padahal kita tahu masyarakat miskin adalah masyarakat paling gigih dalam survive melawan krisis. Lihatlah para PKL. Digusur ribuan kali mereka terus berjualan dengan segala cara dan motif. Justru ditengah keterjepitan dan ancaman hidup mereka memeras otak agar bisa terus makan. Termasuk makan nasi aking atau pelepah pisang. Dengan semangat hidup itu sebenarnya mereka memiliki potensi untuk bangkit dari kemiskinannya. Tinggal bagaimana pemerintah yang bekerja sama dengan ornop pro masyarakat miskin dan partai progresif melakukan pendampingan untuk mengubah nasib mereka baik secara ekonomi maupun politik. Karena itu agenda mendesak dalam penanggulangan kemiskinan adalah melepaskan diri dari cengraman neoliberalisme dan menyusun kembali strategi kemiskinan sesuai kondisi riil masyarakat.
Menghamba pada neoliberalisme terbukti semakin membuat kaum miskin kian terpojok. Lihat saja, mereka makin susah sekolah dan tak bisa dirawat di RS karena tak bisa membayar uang muka, tak ada air bersih dan tak punya rumah. Sebagian yang lain banyak terkena gangguan jiwa. Benar memang dengan kondisi tersebut akan banyak mengucur bantuan-bantuan lembaga donor. Tetapi kesannya bukan membebaskan masyarakat miskin, melainkan menjadikan mereka sebagai tumbal kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pasar.
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Jurnalis. Peneliti pada IRSOD (Institute of Reasearch Social Politic and Democracy).
Minggu, 23 November 2008
Ancaman DBD dan Reformasi Sistem Kesehatan
Ancaman DBD dan Reformasi Sistem Kesehatan
Oleh: Edy Firmansyah
 Musim hujan kembali datang. Tiap kali tiba musim penghujan, yang paling dikwatirkan public selain bencana banjir, juga menyebarnya berbagai macam penyakit. Salah satu penyakit yang kerap menyertai musim penghujan dan banyak memakan korban jiwa adalah Demam Berdarah Dengue (DBD).
Musim hujan kembali datang. Tiap kali tiba musim penghujan, yang paling dikwatirkan public selain bencana banjir, juga menyebarnya berbagai macam penyakit. Salah satu penyakit yang kerap menyertai musim penghujan dan banyak memakan korban jiwa adalah Demam Berdarah Dengue (DBD). Dalam laporan Departemen Kesehatan, penyakit yang disebarkan oleh nyamuk aides aigepty ini sudah menjadi masalah yang endemis di 122 daerah tingkat II, 605 Kecamatan dan 1.800 Desa atau kelurahan. Pasalnya, setiap wabah penyakit ini menyebar, penderitanya meningkat drastis dan tak sedikit yang akhirnya meninggal. Di Jawa Timur, misalnya, pada tahun 2005 terdapat setidaknya 15.257 kasus DBD dengan 266 penderita meninggal. Tahun 2006 jumlah penderita meningkat menjadi 20.375 dengan 251 penderita meninggal.
Data diatas kemungkinan besar bakal meningkat. Pasalnya, program dinas kesehatan terkait pemberantasan demam berdarah masih bersifat konvensional. Misalnya, salah satu andalan pemerintah adalah program fogging. Padahal akibat fogging nyamuk justru mengalami mutasi gen. Dalam hukum darwinian, disebutkan bahwa mahluk hidup bisa bertahan hidup dan berkembang biak bukan lantaran besar dan kuat. Melainkan karena mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hukum darwin ini berlaku juga untuk perkembangan nyamuk aides aigepty.
Regenerasi hasil mutasi gen inilah yang sudah kebal terhadap fogging terus berkembang dan
 menyerang masyarakat. Salah satu contoh kasus yang menarik akibat mutasi gen ini adalah Kabupaten Banyumas. Kabupaten ini pernah dijadikan percontohan pemberantasan DBD tahun 2001. Namun tiba-tiba pada tahun 2002, diserang wabah malaria yang menewaskan ratusan warganya.
menyerang masyarakat. Salah satu contoh kasus yang menarik akibat mutasi gen ini adalah Kabupaten Banyumas. Kabupaten ini pernah dijadikan percontohan pemberantasan DBD tahun 2001. Namun tiba-tiba pada tahun 2002, diserang wabah malaria yang menewaskan ratusan warganya. Karena itu Dinas kesehatan harus segera memikirkan cara pemberantasan DBD selain fogging. Misalnya dengan mengembangbiakkan predator nyamuk dan jentik nyamuk seperti; ikan koi dan katak. Selain cara ini lebih efektif dan aman, baik ikan koi maupun katak dapat dijadikan sumber penghasilan tambahan warga.
 Selain itu, belum dioptimalkannya fungsi pelayanan di tingkatan puskemas juga menjadi faktor meningkatnya jumlah penduduk yang terserang DBD. Puskemas sebagai unit pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebenarnya dapat mengambil fungsi sebagai pengolah informasi ksehatan di satu wilayah. Misalnya, secara berkala petugas di puskemas menyediakan data tentang sejarah penyakit endemi di suatu wilayah, lengkap dengan antisipasi dini dan cara pencegahannya dengan obat-obatan tradisional. Dengan demikian masyarakat sekitar memahami wabah penyakit potensial yang muncul di masyarakat, sehingga jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan. Dengan demikian, masyarakat yang sakit akan semakin berkurang. Bukankah hal tersebut yang sejatinya merupakan keberhasilan sebuah puskesmas disamping kelengkapan fasilitasnya?
Selain itu, belum dioptimalkannya fungsi pelayanan di tingkatan puskemas juga menjadi faktor meningkatnya jumlah penduduk yang terserang DBD. Puskemas sebagai unit pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebenarnya dapat mengambil fungsi sebagai pengolah informasi ksehatan di satu wilayah. Misalnya, secara berkala petugas di puskemas menyediakan data tentang sejarah penyakit endemi di suatu wilayah, lengkap dengan antisipasi dini dan cara pencegahannya dengan obat-obatan tradisional. Dengan demikian masyarakat sekitar memahami wabah penyakit potensial yang muncul di masyarakat, sehingga jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan. Dengan demikian, masyarakat yang sakit akan semakin berkurang. Bukankah hal tersebut yang sejatinya merupakan keberhasilan sebuah puskesmas disamping kelengkapan fasilitasnya? Ironisnya lagi, masyarakat justru diarahkan pada paradigma baru bahwa konsep sakit dan
 penyakit DBD hanya bisa diselesaikan dengan cara mengkonsumsi jasa dan obat-obatan yang diproduksi korporasi farmasi multinasional. Alih-alih menyehatkan masyarakat, para komprador di bidang kesehatan ini justru hendak meraup keuntungan atas pemasaran obat-obatan. Dan lagi-lagi masyarakat awam yang dirugikan.
penyakit DBD hanya bisa diselesaikan dengan cara mengkonsumsi jasa dan obat-obatan yang diproduksi korporasi farmasi multinasional. Alih-alih menyehatkan masyarakat, para komprador di bidang kesehatan ini justru hendak meraup keuntungan atas pemasaran obat-obatan. Dan lagi-lagi masyarakat awam yang dirugikan. Karenanya selama pemerintah tidak mengubah paradigma sehat dan sakit di masyarakat dengan konsep pembelajaran dan pencerdasan masyarakat mengenai seluk beluk penyakit dan cara mengatasinya secara mandiri, maka yang terjadi adalah ketergantungan. Dan jika keadaaan itu dibiarkan, penyakit akan terus menyerang masyarakat. Untuk itu, Melibatkan bakul jamu, sinse pengobatan cina, ahli akupuntur adalah hal yang mendesak. Dari mereka, masyarakat miskin akan belajar banyak hal mengenai penanganan penyakit. Sehingga lambat laun masyarakat akan mampu menangani wabah penyakit dengan kemampuannya sendiri, tanpa harus merepotkan pemerintah.
 Kendala berikutnya adalah mahalnya biaya kesehatan. Benar memang pemerintah sudah memberikan subsidi kesehatan pada masyarakat, yakni berdasarkan UU NO. 45 tahun 1999 pasal 39 tentang kewajiban pemerintah membayar sebagian besar dari iuran layanan kesehatan. Ini bisa dilihat dengan pemberian kastu asuransi kesehatan (Askes) untuk PNS dan kartu Gakin untuk mereka yang miskin. Kendati demikian tarif pelayanan kesehatan justru dibiarkan melonjak antara 25 hingga 75 persen. Akibatnya, hanyak untuk menebus obat generic penurun panas saja, masyarakat tetap merogoh kantong lagi.
Kendala berikutnya adalah mahalnya biaya kesehatan. Benar memang pemerintah sudah memberikan subsidi kesehatan pada masyarakat, yakni berdasarkan UU NO. 45 tahun 1999 pasal 39 tentang kewajiban pemerintah membayar sebagian besar dari iuran layanan kesehatan. Ini bisa dilihat dengan pemberian kastu asuransi kesehatan (Askes) untuk PNS dan kartu Gakin untuk mereka yang miskin. Kendati demikian tarif pelayanan kesehatan justru dibiarkan melonjak antara 25 hingga 75 persen. Akibatnya, hanyak untuk menebus obat generic penurun panas saja, masyarakat tetap merogoh kantong lagi. Makanya jangan heran jika masih banyak masyarakat yang lebih mempercayakan penyembuhan penyakit dengan cara supranatural ( baca; dukun) daripada penyembuhan secara medis (baca; dokter). Di Madura misalnya, tempat praktek dukun yang letaknya jauh di pelosok kampung bisa lebih ramai daripada puskesmas pembantu yang letaknya tepat dipinggir jalan. Karenanya selama biaya kesehatan masih mahal, maka wabah penyakit akan terus menghantui masyarakat.
 Disamping itu rendahnya sisi kemanusiaan kalangan medis juga menjadi penyebab meningkatnya angka DBD dari tahun ke tahun. Sudah bukna rahasia umum lagi kalau orientasi kalangan medis mulai dari perawat, apoteker, bidan hingga dokter adalah orientasi uang. Mereka akan memberikan pelayanan prima pada pasien atau penderita yang berkantong tebal. Padahal menurut Patch Adams dalam bukunya Kisah Inspiratif Seorang Dokter Eksentrik yang Menyembuhkan Penyakit dengan Humor dan Kebahagiaan praktek kedokteran yang ideal adalah penyembuhan yang baik adalah dengan interaksi antarmanusia yang penuh kasih sayang, bukan transaksi bisnis.
Disamping itu rendahnya sisi kemanusiaan kalangan medis juga menjadi penyebab meningkatnya angka DBD dari tahun ke tahun. Sudah bukna rahasia umum lagi kalau orientasi kalangan medis mulai dari perawat, apoteker, bidan hingga dokter adalah orientasi uang. Mereka akan memberikan pelayanan prima pada pasien atau penderita yang berkantong tebal. Padahal menurut Patch Adams dalam bukunya Kisah Inspiratif Seorang Dokter Eksentrik yang Menyembuhkan Penyakit dengan Humor dan Kebahagiaan praktek kedokteran yang ideal adalah penyembuhan yang baik adalah dengan interaksi antarmanusia yang penuh kasih sayang, bukan transaksi bisnis. Karenanya kaum profesional di bidang kesehatan harus ’berani’ mengulurkan tangan pada pasien yang menunjukkan rasa sakit dan kerapuhan mereka. Demi kesehatan pasien; staf, dokter harus berusaha keras membangun persahabatan dengan pasien secara mendalam. Sebab persahabatan adalah obat paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit. Dengan demikian penyakit apapun—termasuk DBD—akan semakin mudah diberantas.
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Pemerhati Kesehatan Masyarakat. Peneliti pada IRSOD ( Institute of Reasearch Social Politic and Democracy). Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.
Menghargai Rakyat Sebagai Pahlawan Sejati
Oleh: Edy Firmansyah
 Pahlawan masih sering diidentikkan dengan seseorang yang memegang senjata dan terjun di medan perang serta bertempur habis-habisan melawan musuhnya. Bahkan untuk menjadi pahlawan orang harus terlebih dahulu gugur akibat peluru atau senjata musuh-musuhnya.
Pahlawan masih sering diidentikkan dengan seseorang yang memegang senjata dan terjun di medan perang serta bertempur habis-habisan melawan musuhnya. Bahkan untuk menjadi pahlawan orang harus terlebih dahulu gugur akibat peluru atau senjata musuh-musuhnya. Karena itu jangan heran jika setiap memperingati hari-hari besar yang terkait erat dengan jasa para pahlawan, semisal; Memperingati Proklamasi Kemerdekaan hingga hari Pahlawan pada 10 November yang menjadi tujuan utama mengenang jasa para pahlawan adalah para veteran perang. Makanya tak heran jika Taman Makam pahlawan (TMP) jadi jujukan untuk menghormati pahlawan. Sebab di sanalah jasad para pahlawan disemayamkan.
Padangan di atas tidak sepenuhnya keliru. Hanya saja terkesan terlalu sempit. Akibatnya gelar kepahlawanan hanya dapat diraih oleh segelintir orang saja. Yakni mereka yang memanggul senjata atau mereka yang terlibat langsung dengan hal ihwal mengenai kenegaraan. Mereka inilah yang ketika meninggal dan hendak disemayamkan pantas diiringi dengan upacara dan tembakan kehormatan.
Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Pahlawan sejati adalah seseorang atau mereka yang telah memperlihatkan sikap-sikap unggul dan terpuji dalam keberanian, kepeloporan, serta kerelaan berkorban dalam membela atau memperjuangkan kebenaran dan kepentingan rakyat kebanyakan. Bahkan mereka yang berkarater tinggi, berani, tenang dan dingin ditengah kemelut apapun, menempatkan manusia dalam martabatnya yang tinggi, tidak kemaruk harta, tidak menonjol-nonjolkan jasanya sendiri serta rendah diri juga pantas di sebut pahlawan.(Jacob Sumardjo, 2002)
Nah, dengan pemahaman yang lebih luas mengenai pahlawan tersebut, peluang jadi pahlawan
 menjadi terbuka bagi setiap orang tanpa harus mengangkat senjata apalagi mati di medan pertempuran. Sebutan atau gelar pahlawan terbuka bagi setiap orang asalkan ia memiliki sikap-sikap yang unggul dan terpuji dalam keberanian, kepeloporan, dan kerelaan berkorban dalam membela kebenaran serta memperjuangkan kepentingan seluruh manusia.
menjadi terbuka bagi setiap orang tanpa harus mengangkat senjata apalagi mati di medan pertempuran. Sebutan atau gelar pahlawan terbuka bagi setiap orang asalkan ia memiliki sikap-sikap yang unggul dan terpuji dalam keberanian, kepeloporan, dan kerelaan berkorban dalam membela kebenaran serta memperjuangkan kepentingan seluruh manusia.Pertanyaannya sekarang, siapakah yang memenuhi semua syarat untuk menjadi pahlawan sejati di negeri ini? Jawabannya adalah rakyat.
Kisah rakyat adalah kisah tentang kebersahajaan kehidupan yang penuh keikhlasan, pahit getirnya hidup serta kesadaran akan dirinya sebagai kawulo alit, sebagai rakyat bawah, rakyat kecil. Mereka tidak pernah menuntut macam-macam, apalagi minta disebut dan dihargai sebagai pahlawan. Mereka bukan orang yang gila penghargaan, bukan tipe orang yang gila sanjungan. Meski begitu mereka mampu menggerakkan sejarah.
Karenanya mengingkari keberadaan rakyat adalah dosa besar yang tak akan termaafkan. Tak ada bangsa yang mampu berdiri tegak tanpa keterlibatan rakyat. Dalam kisah-kisah perjuangan, keterlibatan rakyat adalah fakta mutlak. Partisipasi, peranan dan keterlibatan rakyat dalam merintis, memproklamasikan, mempertahankan dan mengembangkan negeri ini tak bisa dipandang sebelah mata. Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan RI, tidak bisa ada dan terjadi begitu saja tanpa partisipasi rakyat. Bahkan peristiwa 10 November 1945 yang memakan korban sekitar 6.000 jiwa tewas tidak mungkin dikenang tanpa keterlibatan rakyat, baik secara fisik mental maupun material.
 Ironisnya, eksistensi rakyat kian hari kian terpinggirkan, bahkan terlupakan. Di tangan partai politik, elite politik, wakil rakyat, lembaga swadaya masyarakat rakyat menjadi komoditas yang terus-menerus dieksploitasi tanpa henti. terus-menerus berkoar-koar memperjuangkan nasib rakyat tanpa ada realisasinya. Istilah rakyat lebih banyak diomongkan ketimbang diperjuangkan. Rakyat bagai barang dagangan yang ramai dan laris diperjualbelikan.
Ironisnya, eksistensi rakyat kian hari kian terpinggirkan, bahkan terlupakan. Di tangan partai politik, elite politik, wakil rakyat, lembaga swadaya masyarakat rakyat menjadi komoditas yang terus-menerus dieksploitasi tanpa henti. terus-menerus berkoar-koar memperjuangkan nasib rakyat tanpa ada realisasinya. Istilah rakyat lebih banyak diomongkan ketimbang diperjuangkan. Rakyat bagai barang dagangan yang ramai dan laris diperjualbelikan. Partai politik ramai berkotbah di mana-mana, mengobral janji dengan mengatasnamakan dan memperjuangkan rakyat, kelak jika parpol menang aspirasi rakyat akan dikedepankan. Kenyataannya, saat parpol ada di lingkaran kekuasaan, rakyat pun terlupa dari ingatan.
Elite politik juga senada. Berkampanye atas nama rakyat tapi tuli dan buta terhadap aspirasi rakyat. Mereka asyik dengan kekuasaan. Mmeraup keuntungan sebanyak-banyaknya selagi sempat. Lembaga swadaya masyarakat tak henti-hentinya berkoar-koar dan rajin membuat proposal yang konon untuk kepentingan rakyat kepada lembaga donor asing. Sementara masyarakat semakin sesak napas karena lilitan kemiskinan, mahalnya kebutuhan hidup, ketidakadilan, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan lainnya semakin kencang.
Karena itu peringatan Hari Pahlawan kali ini hendaknya dijadikan momentum untuk berefleksi, sudahkah penguasa negeri ini menghormati pahlawan sejatinya? Jika tidak, tak salah jika kemudian masyarakat luas mengutuk pemimpin negeri ini sebagai segolongan orang yang durhaka dan tak tahu terima kasih.***
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Jurnalis Tabloid JEJAK. Peneliti pada IRSOD (Institute of Reasearch Social Politic and Democracy).
Jumat, 21 November 2008
Perempuan dan Kekerasan Terhadap Anak
Dimuat di RADAR SURABAYA, 07 November 2008
Perempuan dan Kekerasan Terhadap Anak
Oleh: Edy Firmansyah Anak-anak Indonesia masih belum sepenuhnya aman dari tindak kekerasan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak juga tak cukup ampuh menjadi perisai bagi anak-anak. Buktinya, kekerasan masih terus menjadi hantu bagi anak-anak.
Anak-anak Indonesia masih belum sepenuhnya aman dari tindak kekerasan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak juga tak cukup ampuh menjadi perisai bagi anak-anak. Buktinya, kekerasan masih terus menjadi hantu bagi anak-anak.
Ironisnya, berdasarkan data sekitar 60 persen pelaku tindak kekerasan terhadap anak justru dilakukan perempuan. Tindakan Nunik Wijaya, warga Kembang Jepun, Surabaya, yang dengan tega menyekap dan memukuli anak bungsunya, Andrew Louis, 9, hingga menangis dan menjerit kesakitan (Radar Surabaya, 5/11/08) merupakan puncak gunung es kekerasan perempuan terhadap anak-anak. Artinya, selain Nunik masih banyak perempuan lain yang tega berlaku kejam pada anak-anak.
Pertanyaannya mengapa perempuan yang kerap menjadi pelaku tindak kekerasan pada anak-anak? Bukankah perempuan selalu identik dengan sifatnya yang lemah lembut, penuh cinta kasih, cinta damai dan selalu mengutamakan keselamatan?
Menurut Dom Helder Camara dalam bukunya Spiral Kekerasan, kekerasan tak pernah berdiri sendiri. Ia lahir menyusul, dan menjadi rantai fantasi berikutnya dari kekerasan-kekerasan terdahulu yang telah berjalin-kelindan. Lewat penelitiannya di Amerika Latin, Camara menerangkan bagaimana kekerasan itu berkelindan. Awalnya kekerasan lahir dibidani oleh egoisme para penguasa dan kelompok-kelompok yang rakus. Berikutnya kekerasan pun muncul sebagai jawaban dari para pejuang keadilan yang mengangkat senjata untuk menumbangkan para penguasa lalim itu. Kekerasan akan kembali muncul sebagai satu-satunya jalan berpikir yang ada dari para penguasa untuk menumpas bentuk kekerasan kedua. Begitulah seterusnya, hingga nyaris tak henti-hentinya darah mengalir untuk menyuburkan dendam yang tak kunjung menuntas. Mirip seperti kisah keris Empu Gandring, kekerasan akan terus memakan korban jiwa, tidak hanya tujuh turunan tetapi sampai akhir masa.
Jika dikaitkan dengan kondisi perempuan Indonesia analisa Camara menunjukkan kebenarannya. Perempuan Indonesia tak lepas dari penindasan. Dari sebuah riset disebutkan bahwa setiap hari ada kasus pemerkosaan terhadap perempuan. Bahkan ada yang menemukan fakta lebih hebat lagi bahwa setiap 6 jam terjadi perkosaan seksual. Belum lagi kasus yang tidak pernah disadari orang sebagai kasus yakni pelecehan seksual, tampaknya sudah menjadi kegiatan spontanitas yang dilakukan dimana-mana. Daftar penindasan bisa bertambah panjang kalau kita memasukkan kasus perdagangan perempuan sebagai budak seks, hingga penganiayaan terhadap istri maupun pembantu rumah tangga.
kebenarannya. Perempuan Indonesia tak lepas dari penindasan. Dari sebuah riset disebutkan bahwa setiap hari ada kasus pemerkosaan terhadap perempuan. Bahkan ada yang menemukan fakta lebih hebat lagi bahwa setiap 6 jam terjadi perkosaan seksual. Belum lagi kasus yang tidak pernah disadari orang sebagai kasus yakni pelecehan seksual, tampaknya sudah menjadi kegiatan spontanitas yang dilakukan dimana-mana. Daftar penindasan bisa bertambah panjang kalau kita memasukkan kasus perdagangan perempuan sebagai budak seks, hingga penganiayaan terhadap istri maupun pembantu rumah tangga.  Tak hanya itu perempuan masih mengalami penghancuran identitas perempuannya sehubungan dengan otonomi ekonomi, politik dan budayanya. Perempuan masih didefinisikan menjadi pelengkap penderita para patriakh yang bisa berbentuk individu laki-laki, cara pandang laki-laki, system yang memberi keuntungan pada laki-laki, pemerintah, dan Negara yang didefinisikan sebagai bapak, pejabat, dan aparat yang benar-benar melaksanakan peran “bapak”(Ruth Indah Rahayu dalam Pramoedya Ananta Toer, 2006). Parahnya lagi, para perempuan tidak sadar bahwa dirinya diekspolitasi. Mereka seakan pasrah saja bahwa keadaan yang menimpa dirinya adalah kodrat.
Tak hanya itu perempuan masih mengalami penghancuran identitas perempuannya sehubungan dengan otonomi ekonomi, politik dan budayanya. Perempuan masih didefinisikan menjadi pelengkap penderita para patriakh yang bisa berbentuk individu laki-laki, cara pandang laki-laki, system yang memberi keuntungan pada laki-laki, pemerintah, dan Negara yang didefinisikan sebagai bapak, pejabat, dan aparat yang benar-benar melaksanakan peran “bapak”(Ruth Indah Rahayu dalam Pramoedya Ananta Toer, 2006). Parahnya lagi, para perempuan tidak sadar bahwa dirinya diekspolitasi. Mereka seakan pasrah saja bahwa keadaan yang menimpa dirinya adalah kodrat.
Dengan kata lain, menurut Gayatri Spivak dalam sebuah artikelnya yang booming dengan judul ‘Can The Subaltern Speak ?’, dijelaskan bahwa kaum perempuan merupakan kaum subaltern. Perempuan adalah manusia yang kehilangan suara kemanusiaannya.
Sikap diam itulah, dalam kacamata psikologi, kemudian menyebabkan akumulasi kemarahan bertumpuk dalam alam bawah sadar perempuan. Menurut Freud, sang psikolog analis, pengalaman traumatis yang telah tersimpan jauh di alam bawah sadar seseorang dalam kondisi tertekan akan menciptakan prilaku menyimpang melebihi dari efek trauma yang pernah dialaminya. Bukankah kerap juga kita dengar ada perempuan yang nekat membunuh anaknya sendiri? Juga tak jarang kita baca di media massa perempuan yang membakar suaminya sendiri?
Tindak kekerasan yang dilakukan perempuan terhadap anak-anak juga merupakan bentuk eskapisme akibat dari penindasan yang dilakukan terhadap perempuan. Sayangnya, penindasan atau ekploitasi yang kerap mereka terima dari hukum patriakat justru mereka lampiaskan pada anak-anak. Baik itu pembantu yang masih berusia dini, anak tiri maupun anak kandung sendiri. Pasalnya, anak-anak merupakan mahkluk paling lemah yang gampang dijadikan pelampiasan emosi.
eskapisme akibat dari penindasan yang dilakukan terhadap perempuan. Sayangnya, penindasan atau ekploitasi yang kerap mereka terima dari hukum patriakat justru mereka lampiaskan pada anak-anak. Baik itu pembantu yang masih berusia dini, anak tiri maupun anak kandung sendiri. Pasalnya, anak-anak merupakan mahkluk paling lemah yang gampang dijadikan pelampiasan emosi.
Karena itu, satu-satunya cara mengakhiri tindak kekerasan adalah dengan memotong siklus kekerasan itu sendiri. Tentu saja tidak cukup dengan menghukum para pelakunya saja. Lebih dari itu, para baik para korban maupun pelaku harus mendapatkan pendampingan dan terapi psikologi yang dalam. Sebab—meminjam analisa Freud—pelaku tindak kekerasan pasti pernah mengalami kekerasan serupa di masa lalunya. Sedangkan korban pasti mengalami trauma alam bawah sadar. Karenanya selama efek  traumatis yang terbangun dalam alam bawah sadarnya tidak dibongkar, tidak menutup kemungkinan ketika dewasa nanti kekerasan serupa akan dilakukan pada anaknya.
traumatis yang terbangun dalam alam bawah sadarnya tidak dibongkar, tidak menutup kemungkinan ketika dewasa nanti kekerasan serupa akan dilakukan pada anaknya.
Yang terakhir adalah membangunkan kembali kesadaran masyarakat yang telah lama mati, bahwa kekerasan apapun bentuknya adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan. Dan ketika pelanggaran itu terjadi, baik di lingkungan sekolah, rumah tangga maupun tetangga dan kerabat sendiri menjadi urusan kemanusiaan dan sudah selayaknya ditindak tegas. Sebab semakin sering kita atau anak-anak kita mengalami atau minimal menyaksikan tindak kekerasan, maka kekerasan akan terus menjadi bagian dari kehidupan kita bahkan menjadi budaya bangsa kita. ***
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Jurnalis. Pemerhati Masalah Psiko-Sosial. Peneliti pada IRSOD (Institute of Reasearch Social Politic and Democracy).
Kamis, 13 November 2008
Mutilasi dan Historiografi Kekerasan Masyarakat
Dimuat di BALI POST, 06 November 2008
Mutilasi dan Historiografi Kekerasan Masyarakat
Oleh Edy Firmansyah*) Akhir-akhir ini peristiwa pembunuhan, khususnya yang disertai mutilasi, kerap terjadi. Peristiwa tersebut terjadi di kota besar dan merambah ke daerah-daerah. Di Bali baru-baru ini kita dikejutkan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala. Mayat tanpa kepala yang ditemukan di Pering, Blahbatuh, Gianyar adalah Rizki bin Jaka alias Abot (29) berasal dari Desa Kademangan, Cisauk, Tangerang. Abot tinggal di Perumahan Dalung Indah, Badung. Pelakunya adalah SU (33) sekampung dengan korban, yang kos di Banjar Tegeh Sari, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar Barat.
Akhir-akhir ini peristiwa pembunuhan, khususnya yang disertai mutilasi, kerap terjadi. Peristiwa tersebut terjadi di kota besar dan merambah ke daerah-daerah. Di Bali baru-baru ini kita dikejutkan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala. Mayat tanpa kepala yang ditemukan di Pering, Blahbatuh, Gianyar adalah Rizki bin Jaka alias Abot (29) berasal dari Desa Kademangan, Cisauk, Tangerang. Abot tinggal di Perumahan Dalung Indah, Badung. Pelakunya adalah SU (33) sekampung dengan korban, yang kos di Banjar Tegeh Sari, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar Barat.  Sejak dibukanya keran demokrasi dan kebebasan, televisi bukannya memberikan konter terhadap segala praktik kekerasan di berbagai pelosok Tanah Air, malah menjadikannya sebagai komoditas hiburan. Kekerasan dalam film, iklan dan berita dipertontonkan pada masyarakat secara vulgar yang tujuan utamanya ialah mengejar rating dan sukses pasar. Lihat saja, dalam berita-berita kriminal dengan vulgar menayangkan aksi tembak-menembak dengan penjahat, modus operandi para penjahat dan pembunuh tanpa sensor sedikit pun. Ditambah lagi dengan tayangan sinetron yang penuh adegan berdarah-darah dan berbau mistis semakin menyemarakkan ajang kekerasan.
Sejak dibukanya keran demokrasi dan kebebasan, televisi bukannya memberikan konter terhadap segala praktik kekerasan di berbagai pelosok Tanah Air, malah menjadikannya sebagai komoditas hiburan. Kekerasan dalam film, iklan dan berita dipertontonkan pada masyarakat secara vulgar yang tujuan utamanya ialah mengejar rating dan sukses pasar. Lihat saja, dalam berita-berita kriminal dengan vulgar menayangkan aksi tembak-menembak dengan penjahat, modus operandi para penjahat dan pembunuh tanpa sensor sedikit pun. Ditambah lagi dengan tayangan sinetron yang penuh adegan berdarah-darah dan berbau mistis semakin menyemarakkan ajang kekerasan.
Kedua, mempresentasikan program kekerasan meningkatkan perilaku agresif. Ketiga, memperlihatkan secara berulang-ulang tayangan kekerasan penyebabkan ketidakpekaan terhadap kekerasan dan penderitaan korban.
Disamping itu negara sebenarnya memiliki andil lahirnya tindak kekerasan di masyarakat. Sebab, kekerasan adalah perkara yang sangat diabaikan dalam pemikiran dan penelitian mengenai Indonesia. Padahal sudah dapat dipastikan --sekalipun tanpa studi dan penelitian -- bahwa kekerasan adalah gejala yang paling bertahan dan berkelanjutan dalam kehidupan politik negeri ini. Bahkan, kekerasan belum pernah diatasi dengan memuaskan dan beradab selama sekurang-kurangnya empat abad terakhir di Nusantara (Kleden, 2004;208).
Negara masih kerap menggunakan cara-cara kekerasan untuk menciptakan 'kesejahteraan' dan rasa 'damai' dalam masyarakat. Sehingga yang terjadi kemudian kekerasan di negeri ini bagaikan sebuah kutukan keris Empu Gandring. Kekerasan akan terus memakan korban jiwa, tidak hanya tujuh turunan tetapi sampai akhir masa. Inilah yang disebut Dom Helder Camara sebagai spiral kekerasan. Ia lahir menyusul, dan menjadi rantai fantasi berikutnya dari kekerasan-kekerasan terdahulu yang telah berjalin-kelindan.
Kekerasan di Indonesia sudah terjadi sejak zaman raja-raja di Nusantara. Berdirinya candi-candi, misalnya, bukanlah seperti yang diceritakan dalam hikayat atau cerita-cerita rakyat yang kita kenal di masa kecil. Menurut para sejarawan, pembangunan candi justru melibatkan ratusan bahkan ribuan masyarakat yang dipaksa menghamba pada raja-raja. Dengan kata lain megahnya Candi Borobudur dan Prambanan sebenarnya tak lepas dari pengorbanan rakyat dengan keringat dan darah. Kekerasan model ini terus berlanjut pada era kekuasaan kolonial Belanda dan Jepang.
Memasuki zaman kemerdekaan tidak berarti menurunnya kekerasan. Setelah Westerling muncul sebagai koboi yang membantai ribuan orang hanya untuk membuktikan kepandaiannya menembakkan senjata api, muncullah berbagai gerakan bersenjata yang kemudian juga dihadapi dengan kekerasan oleh pemerintah Jakarta.
Ketika orde baru lahir kekerasan justru kian bergelora, menggunakan kekerasan politik justru untuk melanggengkan kekuasannya. Peristiwa G-30-S adalah salah satu bukti lahirnya orde baru dengan lumuran darah.
Sampai akhirnya orde baru tumbang, kekerasan terus saja tegak berdiri di negeri ini. Sudah empat kali pemimpin di negeri ini diganti pasca-Soeharto. Tetapi belum mampu memutus mata rantai kekerasan. Malah kekerasan seakan memberi warna pada setiap perjalanan pemerintahan pemimpin baru.  Karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah taktis untuk segera memotong mata rantai kekerasan di negeri ini. Memang penting memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku tindak kekerasan, baik masyarakat maupun aparat tanpa pandang bulu. Namun semua itu tidak cukup efektif jika negara tidak memberi teladan untuk menghentikan kekerasan dalam segala bentuknya. Bukankah hingga kini negara kerap melakukan penggusuran, perampasan hak, hingga kekerasan pada demonstran lewat kekuatan koersifnya?
Karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah taktis untuk segera memotong mata rantai kekerasan di negeri ini. Memang penting memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku tindak kekerasan, baik masyarakat maupun aparat tanpa pandang bulu. Namun semua itu tidak cukup efektif jika negara tidak memberi teladan untuk menghentikan kekerasan dalam segala bentuknya. Bukankah hingga kini negara kerap melakukan penggusuran, perampasan hak, hingga kekerasan pada demonstran lewat kekuatan koersifnya?
Jika negara sudah mampu menjadi ujung tombak gerakan antikekerasan maka pendidikan humanisme bagi masyarakat dan aparat akan optimal dilaksanakan. Tanpa itu semua, kekerasan hanyalah tinggal api dalam sekam.
* Penulis, adalah Jurnalis. Pemerhati masalah-masalah psikososial.
Rabu, 12 November 2008
Menyingkap Tabir Keberanian Laskar Mawar
Judul : Laskar Mawar: Drama Perempuan-Perempuan Pelaku Bom Bunuh

Diri di Palestina
Penulis : Barbara Viktor
Penerjemah : Anna Farida
Penerbit : Mizan, Bandung
Cetakan : I, Mei 2008
Tebal : xlii + 404 Halaman
Peresensi : Edy Firmansyah
Perempuan selalu identik dengan sifatnya yang lemah lembut, penuh cinta kasih, cinta damai dan selalu mengutamakan keselamatan. Namun dalam derita penjajahan yang sedemikian panjang perempuan bisa juga mengangkat senjata. Di Palestina, dalam derita penjajahan Israel, telah lama perempuan menjadi pejuang yang tangguh dan tabah. Mereka adalah anak yang menyaksikan ayahnya ditawan, istri yang merelakan suaminya hilang tanpa jejak, ibu yang menguburkan putranya. Bahkan sebagian perempuan Palestina menempuh jalan perjuangan baru. Mereka memilih meledakkan diri sebagai ”Laskar Mawar.”
Adalah Wafa Idris, seorang perempuan berusia 26 tahun yang menjadi pelopor kamikaze perempuan Palestina. Pada siang hari, 27 Januari 2002, ia meledakkan dirinya hingga berkeping-keping di tengah Kota Jerussalem di sebuah pusat perbelanjaan, dan menewaskan seorang lelaki Israel dan melukai 131 orang-orang yang lalu lalang.
Meski ia satu-satunya pelaku bom bunuh diri perempuan yang tidak meninggalkan rekaman pengakuan dalam video tentang aksi bunuh diri yang begitu cepat itu, namun ia telah menjadi contoh bagi sejumlah banyak perempuan di sepanjang Tepi Barat dan Gaza yang telah mencoba menjadi syahidah demi berdirinya negara Palestina yang merdeka. Dengan kata lain, kecintaan pada kematian tiba-tiba meresap dalam diri perempuan Palestina. Perempuan yang sejatinya merupakan penjaga kehidupan (karena lewat rahimnya mampu melahirkan generasi-generasi baru) kini berubah menjadi mesin pembunuh.
Pasalnya, aksi bom bunuh diri ini tidak dilakukan terhadap pangkalan militer, markas pasukan Israel, atau gudang senjata sebagaimana yang dilakukan kamikaze Jepang pada perang dunia kedua. Bom bunuh diri ini dilakukan di pusat-pusat keramaian seperti pasar, Plasa atau gerai makanan dimana penduduk sipil Israel biasa beraktivitas. Makanya tak heran jika korbannya justru bukan tentara, melainkan penduduk sipil seperti; ibu, kakek, nenek bahkan anak-anak yang tidak berdosa.
Parahnya lagi, meski tindakan teror itu mendapat kecaman banyak pihak, sebagian besar penduduk Palestina memuja-muja para ’laskar mawar’ itu sebagai pahlawan. Bahkan kaum ulama Palestina sepakat bahwa mereka yang mati karena aksi bom bunuh diri ini termasuk golongan syahid. Dan mereka yang mati syahid tempatnya di akherat adalah surga.
Sampai disini pertanyaan yang pantas diajukan adalah mengapa para pempuan itu tega menghancurkan tubuhnya sendiri hanya untuk melukai penduduk sipil Israel yang sejatinya tidak berdosa itu? Apa yang mereka pikirkan kala itu? Bukankah kehidupan lebih baik dari kematian. Bahkan mempertahankan hidup jauh lebih penting meski maut sudah diujung mata.
Barbara Viktor, seorang jurnalis spesialis Timur Tengah dan isu-isu perempuan mencoba mengurai pertanyaan-pertanyaan diatas. Lewat buku ini ia mengajak kita menyelami kehidupan perempuan-perempuan pelaku bom bunuh diri itu. Dia meninjau berbagai aspek yang sering tenggelam dalam sensasi berita: kultur, psikologis dan sosiologis perempuan Palestina. Barbara membawa kita menyimak kisah-kisah getir dan konflik-konflik yang membuat ’mawar-mawar’ itu memilih menggugurkan kelopak mereka sendiri dalam sebuah dentuman yang menyentakkan dunia yang tak mengijinkan mereka mekar.
Kenekatan yang dilakukan para perempuan pelaku bom bunuh diri itu tak melulu masalah nasionalisme. Benar memang keinginan untuk merdeka dan terbebas dari penjajahan adalah keinginan setiap manusia. Dan manusia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan kebebasan itu. Namun kebebasan yang diinginkan para perempuan-perempuan itu adalah pembebasan dari budaya patriakat Palestina yang sedemikian ketat. Dalam pandangan patriakat, perempuan tak lebih hanya sekedar perhiasan semata. Kodratnya sebagai manusia yang berhak sejajar dengan laki-laki telah digantungkan di langit-langit kamar.
Bermula dari kekerasan struktural yang diciptakan penguasa-penguasa Palestina. Kekerasan struktural itu dapat dirasakan pada kemunculan hegemoni bahasa, dimana hanya yang berkuasa yang berhak memberikan tafsiran atas realitas yang terjadi dalam masyarakat.
Misalnya, perempuan Palestina yang tidak menikah harus hidup dibawah aturan sosial dan agama yang ketat: jika berpendidikan tinggi, ia dianggap abnormal; jika memandangi laki-laki, ia terancam dikucilkan; jika menolak menikah, ia dianggap lepas kendali; jika tidur dengan laki-laki, khususnya jika hamil, ia adalah aib bagi keluarga dan bisa mati di tangan kerabat laki-lakinya (hal. 257). Satu-satunya cara agar perempuan bisa duduk sejajar dengan laki-laki adalah dengan menjadi syahidah, mengorbankan jiwa dan raganya demi bangsanya. Dengan mati syahid kaum perempuan bisa langsung ditempatkan di surga dan bisa menentukan nasibnya sendiri.
Pandangan itulah yang menghantarkan Wafa Idris, Zina dan Darine menjadi pelaku bom bunuh diri itu. Wafa Idris merasa hidupnya hancur setelah suaminya terpaksa menceraikannya karena ia divonis mandul (hal 16-66). Zina yang ketahuan hamil diluar nikah dibuang orang tuanya dalam kancah pertempuran hanya untuk menutup aib(159-195), dan Darine memilih mati karena terus menerus ditekan untuk menikah dengan pria yang sama sekali tidak dicintainya(124-141).
Meski sejatinya buku ini merupakan sebuah liputan investigasi, pembaca tidak akan merasakan kejenuhan sebagaimana halnya membaca sebuah berita umumnya. Karena Barbara menggunakan teknik jurnalisme sastrawi yang dikenalkan sejak tahun 1960-an oleh Tom Wolfe. Wawancaranya dilakukan dengan puluhan, bahkan ratusan narasumber. Risetnya tidak main-main. Waktu bekerjanya berbulan-bulan. Dan hasilnya, sebuah tulisan yang panjang yang memadukan teknik jurnalisme ketat serta gaya bercerita novel. Bahkan buku ini berhasil menggambarkan dengan begitu jelas posisi kaum perempuan Palestina ditengah kepungan penjajahan Israel dan dibawah tekanan budaya Patriakat.
TENTANG PENULIS
**Edy Firmansyah adalah Jurnalis. Pustakawan di Sanggar Bersastra Kita (SBK), Madura.