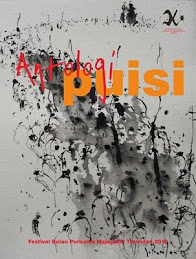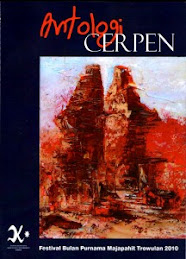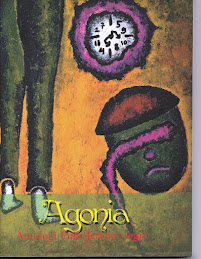DIMUAT DI HARIAN SURYA, 30 Juni 2008
Oleh: Edy Firmansyah Keterpurukan sejumlah bangsa di berbagai belahan bumi dalam kubangan kemiskinan, pendidikan, dan kematian mulai menjadi perhatian serius dunia. Pasalnya, keterpurukan tersebut mengancam keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Karenanya pada abad 21 badan PBB mengumpulkan kepala pemerintahan untuk menandatangani pembangunan milenium (MDGs) di New York. Tujuannya, tak lain untuk menyelamatkan bangsa (save nations).
Keterpurukan sejumlah bangsa di berbagai belahan bumi dalam kubangan kemiskinan, pendidikan, dan kematian mulai menjadi perhatian serius dunia. Pasalnya, keterpurukan tersebut mengancam keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Karenanya pada abad 21 badan PBB mengumpulkan kepala pemerintahan untuk menandatangani pembangunan milenium (MDGs) di New York. Tujuannya, tak lain untuk menyelamatkan bangsa (save nations).
Setidaknya ada delapan tujuan MDGs. Namun dari jumlah itu, ada tiga tujuan yang terkait dengan keberlangsungan hidup. Yakni, penurunan angka kematian ibu dan anak, memerangi HIV/AIDS dan memerangi malaria.
Namun tulisan ini tidak akan membahas semua tujuan pokok MDGs, melainkan fokus pada perang melawan malaria. Malaria merupakan penyakit yang sangat cepat menular dan masih merupakan masalah dunia. Diperkirakan 1,2 juta miliar manusia tinggal di daerah endemis malaria. Bahkan menurut laporan WHO 1998 setidaknya 1,50-2,70 juta jiwa manusia meninggal akibat penyakit malaria.
Di Indonesia sendiri serangan malaria tak kalah ganasnya. Ada sekitar 15 juta jiwa penduduk yang menjadi korban malaria. Dan 30 ribu jiwa diantaranya meninggal dunia. Hal itu terjadi terus hampir setiap tahunnya.
Nah, pertanyaan mendasar yang diajukan adalah apa penyebab malaria menjadi penyakit yang ’mematikan’ terutama di Indonesia? Ternyata menurut Gutomo Priyatmono, penulis buku Bermain Dengan Kematian, Potret Kegagalan Pembangunan Kesehatan Monokultur di Negeri 1001 Penyakit, keganasan malaria bukan hanya disebabkan oleh serangan nyamuk semata. Melainkan juga karena Pembangunan kesehatan modern di Indonesia menempatkan dirinya sebagai sebuah pasar. 
Dalam pasar, semuanya dikelola berdasarkan untung rugi. Mulai dari obat-obatan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Rumah sakit, puskesmas, dokter, termasuk didalamnya apotek menjadi kekuatan legal yang menentukan sehat tidaknya seseorang. Akibatnya, program bio-medis modern yang bertujuan untuk kepentingan peningkatan kesehatan justru membuat masyarakat mengalami hal lebih buruk.
Berdasarkan penelitiannya tentang kasus pemberantasan penyakit malaria di dua wilayah pedesaan yang terletak di perbukitan Manoreh Kabupaten Kulon Progo Propinsi DIY, yaitu Hargowilis dan Hargotirto, menunjukkan bahwa program pemberantasan malaria di dua wilayah tersebut belum mampu membawa masyarakat mempunyai pengetahuan baru tentang penyakit dan malaria. Malah sebaliknya, menjerumuskan masyarakat pada ketidakpastian dalam pencegahan, pengobatan dan penyembuhan penyakit tersebut.(Priyatmono, 2007;252) Contoh dari hal diatas adalah penanganan penyakit seperti demam berdarah dan malaria yang selalu didasarkan pada standar operasional yang sesuai dengan aturan Departemen Kesehatan. Inilah yang disebut Ivan Illich sebagai monopoli bio medis terhadap masyarakat. Usaha menyehatkan dengan teknologi, seperti pengasapan dan pemasangan kelambu berada di tangan penguasa medis.
Contoh dari hal diatas adalah penanganan penyakit seperti demam berdarah dan malaria yang selalu didasarkan pada standar operasional yang sesuai dengan aturan Departemen Kesehatan. Inilah yang disebut Ivan Illich sebagai monopoli bio medis terhadap masyarakat. Usaha menyehatkan dengan teknologi, seperti pengasapan dan pemasangan kelambu berada di tangan penguasa medis.
Padahal keterlibatan aktif masyarakat sebenarnya merupakan pencegah utama dari menjalarnya wabah. Sebab masalah sehat, sakit dan penyakit erat hubungannya dengan kepercayaan, sosial dan psikologi masyarakat.
Karenanya Priyatmoko menuding yang paling bertanggung jawab atas merebaknya penyakit malaria di Indonesia (bisa jadi di negara lainnya) adalah para ahli bidang kesehatan dan para pengambil kebijakan yang berada di Departemen Kesehatan RI. Sebab model pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia selama hampir 40 tahun hanya sekedar mengedepankan rasionalitas tujuan (instrumental rationality) yang mengarahkan pembangunan pada terminologi construction. Dengan kata lain, pembangunan kita adalah pembangunan yang mengutamakan hasil kuantitatif (material) (hal. 22). Yang terjadi kemudian hasil pembangunan justru bermuara pada depedensi, eksploitasi dan marginalisasi masyarakat. Pembangunan model ini sudah merambah hampir di semua sektor. Termasuk juga di sektor kesehatan.
Betapa tidak, program pemberantasan malaria yang dipahami masyarakat di Hargowilis dan Hargotirto sebatas kegiatan fisik dan bantuan. Kegiatan fisik dan bantuan itu berupa penyemprotan, pembagian kelambu, pembagian poster kampanye anti malaria dan pembagian obat gratis. Tidak lebih.
Sedangkan yang dibutuhkan masyarakat dalam penanganan dan pencegahan penyakit adalah wawasan dan pengetahuan yang lebih mengenai seluk beluk penyakit. Sehingga penanganan dan pencegahan bisa dilakukan dengan cara-cara tradisional seperti dengan tanaman jamu, dan lainnya. Sehingga ketika penyakit menyerang, masyarakat sudah mampu melakukan antisipasi dini, tanpa menunggu pertolongan program pemerintah yang kerap terlambat. Tapi sayang, kesempatan untuk mengetahui sistem pengetahuan dibalik bantuan tersebut justru terkunci rapat. Masyarakat justru diarahkan pada paradigma baru bahwa konsep sakit dan penyakti malaria hanya bisa diselesaikan dengan cara mengkonsumsi jasa dan obat-obatan malaria yang diproduksi korporasi farmasi multinasional. Alih-alih menyehatkan masyarakat, para komprador di bidang kesehatan ini justru hendak meraup keuntungan atas pemasaran obat-obatan.
Masyarakat justru diarahkan pada paradigma baru bahwa konsep sakit dan penyakti malaria hanya bisa diselesaikan dengan cara mengkonsumsi jasa dan obat-obatan malaria yang diproduksi korporasi farmasi multinasional. Alih-alih menyehatkan masyarakat, para komprador di bidang kesehatan ini justru hendak meraup keuntungan atas pemasaran obat-obatan.
Karenanya selama pemerintah tidak mengubah paradigma sehat dan sakit di masyarakat dengan konsep pembelajaran dan pencerdasan masyarakat mengenai seluk beluk penyakit dan cara mengatasinya secara mandiri, maka yang terjadi adalah ketergantungan. Dan jika keadaaan itu dibiarkan, penyakit akan terus menyerang masyarakat.
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Peneliti pada IRSOD (Institute of Reaseach Social Politic and Democracy) Jakarta. Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.
WAKTU
JEJAK
- Artikel (93)
- Cerpen (20)
- Esai Budaya (31)
- Jendela Rumah (24)
- Kesehatan Masyarakat (5)
- Pendidikan (10)
- PUISI (71)
- Resensi Buku (25)
JEDA
Senin, 30 Juni 2008
Malaria dan Pembangunan Kesehatan Monokultur
Rabu, 25 Juni 2008
PSB Tak Cukup Hanya Mengandalkan Gaji ke-13
Dimuat di METROPOLIS, JAWA POS, 24 Juni 2008
PSB Tak Cukup Hanya Mengandalkan Gaji ke-13
Oleh: Edy Firmansyah Tak lama lagi musim Penerimaan Siswa baru (PSB) segera tiba. Terutama di kota-kota besar seperti Surabaya , kita akan saksikan ramainya lembaga pendidikan diserbu orang tua siswa. Tentu saja kita patut bergembira karena kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya meningkat.
Tak lama lagi musim Penerimaan Siswa baru (PSB) segera tiba. Terutama di kota-kota besar seperti Surabaya , kita akan saksikan ramainya lembaga pendidikan diserbu orang tua siswa. Tentu saja kita patut bergembira karena kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya meningkat.
Tapi kita juga bersedih dan sangat bersedih, karena biaya sekolah pasti semakin mahal. Untuk bersekolah di sekolah favorit seperti di SMA Negeri di Surabaya misalnya, wali murid harus merogoh kocek Rp. 600.000 - Rp. 800.000,- per bulan untuk iuran sekolah. Iuran itu belum termasuk uang seragam, biaya ujian dan lain sebagainya.
Akibatnya bisa ditebak, sekolah-sekolah dengan kualitas bagus (sekolah favorit), akhirnya hanya menjadi tempat bagi kaum yang tidak miskin. Parahnya lagi, orang tua yang kaya juga bisa membeli ”bangku” di sekolah favorit meskipun sang anak tidak lolos tes PSB. Permainan semacam itu terjadi di banyak tempat di seluruh Indonesia , terutama di kota-kota besar. Sebab bagi orang tua murid (juga guru), bersekolah di sekolah favorit merupakan prestise tersendiri.
Sehingga pilihan rakyat miskin untuk dapat terus mengenyam pendidikan jatuh pada sekolah-sekolah gurem yang fasilitasnya sangat memprihatinkan. Tenaga pengajarnya kurang, kursi dan bangku banyak yang rusak. Sedangkan gedung sekolahnya terkesan ringkih. Tetapi apa boleh buat, hanya sekolah itulah yang bisa dijangkau oleh mereka. Ketimbang tidak sekolah. Kasus sekolah nunut di Surabaya merupakan bukti betapa pendidikan yang layak itu hanyalah milik  kelas berpunya.
kelas berpunya.
Kondisi tersebut jelas sebuah ironi. Sebab kalau kita merujuk pada UUD 1945, pendidikan semestinya menjadi milik tiap anggota masyarakat tanpa kecuali. Negara harus menyediakan sarana-sarana pendidikan, termasuk memberikan subsidi memadai agar masyarakat memperoleh kesempatan belajar yang sama kualitasnya. Tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memperhatikan pendidikan. Semua warga negara berhak mengenyam pendidikan yang layak sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tapi UUD dasar dalam realitas hanyalah kertas usang yang tak memiliki kesaktian. Buktinya, sekolah-sekolah dengan mutu baik dan fasilitas lengkap dari TK hingga PT hanya bisa dimasuki oleh anak-anak orang kaya, selebritis, pejabat atau kelas sosial tertentu. Sedangkan anak buruh dan rakyat biasa harus “mengalah” untuk masuk kedalamnya. Dengan satu alasan, mereka tak sanggup membayar biaya sekolah bermutu yang kian hari kian melambung tinggi itu.
Sebenarnya pemerintah telah memberikan keringanan terkait dengan biaya pendidikan, misalnya dengan kucuran Biaya Operasional Sekolah (BOS). Di samping itu para PNS juga disuntik dana ‘segar’ dengan gaji ke-13 (yang rutin dikeluarkan Pemerintah tiap tahun menjelang tahun ajaran baru dimulai). Hasilnya? Memang cukup membantu, terutama wali murid yang kebetulan bekerja sebagai PNS. Namun yang menjadi permasalahan, praktek di lapangan ketika PSB di mulai sering tidak menggembirakan. Benar memang biaya SPP tidak terlalu mahal, tetapi pungutan-pungutan terhadap murid yang sejatinya tidak esensial bagi proses pembelajaran, justru dipertahankan meski lebih mahal dari SPP.
Memang semua orang tahu tidak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan untuk memperoleh ilmu melalui institusi pendidikan bernama sekolah sekalipun. Namun permasalahannya, biaya pendidikan yang mahal, terutama bagi kelas menengah ke bawah, tentu tidak bisa dibenarkan karena secara tak langsung membatasi akses bagi setiap warga negara untuk mendapat pendidikan yang layak dan murah.
Karenanya, dinas Pendidikan harus memberikan peluang yang sama agar sekolah favorit tidak hanya didominasi anak dari orang-orang berpunya. Hal yang paling memungkinkan adalah tes PSB harus fair. Tes ujian PSB harus benar-benar menjadi penentu bagi siswa. Intinya, transparansi dan keterbukaan harus diutamakan. Semua civitas sekolah harus welcome pada siapapun yang dinyatakan lulus dalam tes tersebut. Baik itu yang miskin maupun yang kaya. Mereka punya hak yang sama menikmati segala fasilitas pendidikan yang dibangun pemerintah.  Mengandalkan gaji 13 sebagai satu-satunya subsidi pemerintah untuk meringankan beban pendidikan tak cukup berarti. Karena tiap pencairan dana tersebut kerap diiringi naiknya harga kebutuhan pokok dan melonjaknya biaya pendidikan.
Mengandalkan gaji 13 sebagai satu-satunya subsidi pemerintah untuk meringankan beban pendidikan tak cukup berarti. Karena tiap pencairan dana tersebut kerap diiringi naiknya harga kebutuhan pokok dan melonjaknya biaya pendidikan.
Untuk itu, mensubsidi anak-anak miskin tetapi pintar adalah keharusan pemerintah. Karena anak-anak dengan kemampuan tersebut sejatinya adalah para pekerja keras. Kisah hidup anggota Laskar Pelangi yang ditulis Andrea Hirata adalah sedikit contoh betapa gigihnya semangat belajar masyarakat miskin. Bahkan tokoh Lintang, mampu memiliki pemikiran brilian karena semangat belajarnya tak putus-putus. Dikatakan demikian, karena ditengah-tengah keterhimpitan ekonomi dan minimnya fasilitas, anak-anak tersebut mampu bersaing dengan anak-anak yang memiliki fasilitas lengkap dan dukungan finansial dari orang tua yang mapan secara ekonomis. Bagaimana menurut anda?
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Peneliti pada IRSOD (Institute of Reasearch Social Politic and Democracy). Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember
Selasa, 24 Juni 2008
Mengkaji Ulang Program Karyawisata Bagi Siswa
Dimuat di KOMPAS Edisi Jawa Timur, 24 Juni 2008
Oleh: Edy Firmansyah 
Program karyawisata kembali memakan korban jiwa. Bus wisata Sidomulyo dengan nopol AG 6678 TU yang mengangkut rombongan murid TK Dharma Wanita, Desa Karangdiyeng, Kabupaten Mojokerto, terbakar di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (9/6). Akibat kecelakaan tersebut, dua siswa dan seorang wali siswa terpanggang hidup-hidup. Sedangkan sebelas penumpang lainnya menderita luka bakar (Kompas, 10/06)
Kecelakaan tersebut seakan mengajak kita kembali merenung sejauh mana manfaat program karyawisata sekolah dibandingkan dengan risiko yang harus ditanggung? Pasalnya kecelakaan ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya pada medio tahun 2003 kecelakaan serupa menimpa juga bus pariwisata SMK Yapemda, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, DIY di Situbondo dalam acara karyawisata ke Bali. Dalam kecelakaan tersebut 51 murid dan dua guru SMK Yapemda, serta seorang pemandu wisata tewas.
Memang setelah kecelakaan maut SMK Yapemda itu program karyawisata sempat mendapat kritik tajam banyak kalangan. Bahkan beberapa Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan sempat melarang program tersebut.
Tapi entah mengapa akhir-akhir ini kegiatan tersebut marak hingga akhirnya kembali memakan korban jiwa. Bahkan program ini sudah menjadi rutinitas yang dijalani sekolah-sekolah di Indonesia setiap penutupan tahun ajaran—biasanya setelah ujian atau menjelang kenaikan kelas—sekolah-sekolah banyak mengadakan program karyawisata ke daerah-daerah tujuan wisata. Kota-kota seperti Malang, Yogyakarta, Lamongan, Bali, merupakan kota yang banyak dikunjungi wisata pelajar dari berbagai penjuru daerah.
Komersialisasi Sekolah Sudah diketahui oleh umum bahwa sekolah saat ini bukan saja sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan semata. Lebih dari itu, sekolah juga telah berubah fungsi menjadi ’pasar.’ Dalam logika pasar berlaku hukum ekonomi paling konvensional, yakni bagaimana mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Prilaku pasar yang terjadi di sekolah bisa dilihat dari pengadaan pakaian seragam, jual buku pelajaran, hingga program karyawisata.
Sudah diketahui oleh umum bahwa sekolah saat ini bukan saja sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan semata. Lebih dari itu, sekolah juga telah berubah fungsi menjadi ’pasar.’ Dalam logika pasar berlaku hukum ekonomi paling konvensional, yakni bagaimana mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Prilaku pasar yang terjadi di sekolah bisa dilihat dari pengadaan pakaian seragam, jual buku pelajaran, hingga program karyawisata.
Sebagaimana diutarakan Darmaningtyas pelaksanaan proram karyawisata itu melibatkan jaringan bisnis yang sangat kompleks, mulai dari jasa trasnportasi, katering, tempat pariwisata dan sebagainya. Di setiap bagian itu selalu terbuka celah lebar untuk melakukan transaksi bisnis, baik bagi sekolah secara institusional dan guru secara individual yang mengurusi program tersebut (2004;224). Misalnya ketika melibatkan jasa transportasi yang dipikir pertama kali adalah bagaimana mendapatkan transportasi yang murah, sehingga laba yang didapat bisa lebih besar. Akibatnya faktor keselamatan nyaris terlupakan. Bukankah dalam hukum ekonomi semakin murah suatu barang atau jasa, maka kualitas dari barang atau jasa tersebut semakin diragukan? Tentu saja dalam hal ini yang dirugikan jelas adalah siswa dan wali siswa sebagai konsumen.
Selain abainya faktor keselamatan, sekolah dengan logika pasar cenderung melahirkan siswa-siswa yang konsumtif, rekreatif dan hedonistik dengan cara yang instan. Dalam kasus karyawisata, hal ini bisa dilihat bahwa ternyata program tersebut yang idealnya hendak memadukan pendidikan dengan rekreasi dalam kenyataannya justru lebih mengedepankan unsur rekreatif daripada didaktis.
Siswa diajarkan bagaimana menjadi wisatawan, tanpa pernah dibekali dengan pembelajaran bagaimana bekerja keras. Artinya guru tidak pernah memberikan penjelasan secara detail dan bagaimana menjadi wisatawan seperti orang-orang di negara-negara maju, bahwa untuk menjadi wisatawan yang hanya beberapa hari itu mereka harus bekerja keras terlebih dahulu selama bertahun-tahun dan hasilnya kemudian ditabung untuk rekreasi. Tanpa penjelasan itu, yang ditangkap siswa dari program karyawisata hanyalah kesenangan belaka.
Makanya jangan heran jiwa lulusan sekolah saat ini kerap menggunakan jalan pintas untuk meraih apa yang diinginkannya. Mau bukti? Anggota DPR/DPRD yang kerap melakukan studi banding ke luar negeri: sama- sama memboroskan biaya dengan hasil amat minim merupakan proyeksi bagaimana hasil dari pendidikan yang mengajarkan budaya instan.
Seni sebagai Alternatif
Padahal untuk sekedar mengembangkan wawasan siswa dan menjalin kedekatan antara sekolah, siswa dan wali murid tidak harus dilakukan dengan karyawisata. Banyak alternatif lain yang lebih bermanfaat dan hemat biaya. Misalnya dengan menggelar pagelaran seni di sekolah dengan melibatkan tidak hanya siswa, tetapi juga wali murid dan guru sebagai pemeran utamanya.
Selain itu manfaat seni juga amat besar. Seni menurut Fridrich Schiller (filsuf dari Jerman) merupakan semacam permainan menyeimbangkan segenap kemampuan mental manusia berhubung dengan adanya kelebihan energi yang harus disalurkan. Dengan berkesenian, seseorang diasah kreativitas, perasaan, kepekaan atau sensitifitas kemanusiaanya, sehingga terhindar dari tindakan destruktif, sempit kerdil dan picik. Bahkan jika program seni itu dilakukan dengan intensif dan maksimal, maka merujuk pada pernyataan Fridrich Schiller itu, tak akan lagi ditemukan tawuran antar mahasiswa hanya karena masalah sepele. Juga tidak ada lagi prilaku destruktif lainnya seperti narkoba dam free sex. Sebab kesenian telah memberi ruang bagi penyaluran energi siswa.***
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Peneliti pada IRSOD (Institute of Reasearch Social Politic and Democracy), Jakarta. Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.
Sabtu, 21 Juni 2008
Membangun Kecerdasan Politik Dalam Pilgub Jateng
Dimuat di SUARA KARYA, 20 Juni 2008
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng), tinggal menghitung hari. Atmosfer politik mulai terasa panas. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub dan cawagub) yang berkompetisi mulai menebar pesona, membangun jaringan, mengeruk simpati massa. Polarisasi keberpihakan mulai terasa di masyarakat.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng), tinggal menghitung hari. Atmosfer politik mulai terasa panas. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub dan cawagub) yang berkompetisi mulai menebar pesona, membangun jaringan, mengeruk simpati massa. Polarisasi keberpihakan mulai terasa di masyarakat.
Kondisi tersebut lumrah dalam riak politik. Toh akhirnya keputusan berada di tangan rakyat. Siapa yang menang dan siapa yang kalah ditentukan dalam satu dua menit di bilik suara.
Yang tidak lumrah, justru ketika demokrasi (baca: pilgub) hanya menjadikan masyarakat Jateng tidak lebih dari sekadar bemper politik atau sebagai tumbal kekuasaan.
Hal itulah yang selalu ditakuti Sokrates, salah seorang filsuf Yunani, sejak kemunculan demokrasi pertama kali kira-kira lima abad sebelum tarikh Masehi dalam masa Yunani Antik di Kota Athena, berabad-abad lalu.
Menurut Sokrates, demokrasi memungkinkan suatu wilayah diperintah oleh orang-orang yang tidak prorakyat, hanya karena mendapat banyak dukungan.ز al ini dikarenakan para pemilih cenderung memberikan suaranya kepada orang-orang yang disukai, bukan pada orang-orang yang kompeten. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan justru mengesampingkan nasib kaum marjinal. (Kleden, 2004).
Parahnya lagi, ketakutan Sokrates di atas kerap terjadi pada wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang banyak, tingkat pendidikan rendah, angka buta aksara tinggi, institusi sosial-politik lemah.
Demokrasi gampang dimanipulasi oleh elite-elite politik oportunis dan pemimpin despotik yang menawarkan janji-janji populis agar bisa terpilih sebagai wakil rakyat di parlemen atau pejabat pemerintahan.
Namun, setelah terpilih terbukalah kedok aslinya. Bahwa tujuan para elite politik dan para pemimpin despotik itu merebut kekuasaan, tak lain hanya untuk kepentingan pribadi (memperluas kekuasaan, mencari keuntungan ekonomi, menumpuk materi). Dengan tanpa rasa iba, mereka meninggalkan rakyat yang terus berkubang dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
Dengan menurunnya daya beli masyarakat, melambungnya harga kebutuhan pokok, naiknya ongkos transportasi sebagai imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), jumlah penduduk miskin di Jateng dipastikan akan meningkat tajam.
Kondisi ini tentu saja merupakan potensi besar bagi para pialang politik yang berwatak Machavelian, untuk memanipulasi demokrasi demi suksesnya perebutan kekuasaan, termasuk dengan menciptakan pertentangan, peperangan dan anarkisme. 
Bukankah tindak kriminal, teror, penganiayaan, kekerasan dan konflik yang terus menjadi berita sehari-hari di negeri ini pemicu utamanya lebih disebabkan oleh kemiskinan?
Karena itu, penting kiranya membangun kecerdasaan berpolitik masyarakat Jateng dewasa ini. Karena nuansa demokrasi yang mulai menjalar di segenap sendi kehidupan masyarakat menuntut semua lapisan masyarakat mulai dari arus elite sampai dengan kaum alit untuk peka terhadap politik.
Memang tak mudah membebaskan masyarakat untuk sadar politik. Pasalnya hampir 32 tahun masyarakat hanya dijadikan floating mass (massa mengambang) dalam perpolitikan. Pada masa itu, politik hanyalah urusan kaum elite. Satu-satunya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik adalah ketika pemilu tiap lima tahun sekali.
Sehingga terbangunlah paradigma masyarakat bahwa politik itu hanya pesta-pesta. Gejala semacam ini setidaknya belum terkikis habis hingga saat ini, sehingga kecenderungan politik melahirkan konflik masih sangat besar.
Meski demikian, bukan tidak ada cara menciptakan kecerdasan politik bagi masyarakat. Setidaknya ada tiga cara yang memungkinkan untuk itu. Pertama, komitmen kandidat cagub dan cawagub untuk menerima segala konsekuensi dari pertarungan politik; siap menang dan kalah. Dengan begitu, harapannya terbangunlah kesadaran bahwa menang dan kalah adalah bagian dari kehidupan politik. Harus diterima secara legowo apa pun hasil dari pilgub itu.
Kedua, keterlibatan secara penuh para aktivis mahasiswa, LSM, dan partai politik yang progresif dan memiliki wacana pembebasan rakyat untuk terus mendidik rakyat, untuk cerdas tidak hanya secara didaktis melainkan juga secara politik. Hanya dengan cerdas secara politik peluang terciptanya politik damai tanpa terpengaruh kampanye politisi busuk untuk memanipulasi demokrasi bisa terwujud.
Terakhir adalah media massa. Media massa setidaknya mampu menjadi jembatan guna terciptanya politik damai dalam Pilkada Jateng ini. Karena itu, media massa diharapakan tidak hanya sekadar pintar mengeksploitasi keberaniannya untuk memunculkan isu-isu baru seputar pilkada. Tetapi media massa yang berpengaruh besar terhadap masyarakat harus memulai dengan membuat wacana-wacana pengendalian diri seputar pilkada. Artinya, pers yang bebas adalah pers yang mampu menjadi jalur bagi terciptanya integritas masyarakat.
Dengan keterlibatan penuh ketiga elemen tersebut diharapkan upaya-upaya memanipulasi demokrasi dalam Pilkada Jateng bisa diminimalisasi. Dengan demikian Pilgub Jateng benar-benar merupakan ruang demokrasi rakyat yang sejati. Semoga!***
Tentang Penulis
and Democracy (Irsod), Jakarta. Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.
Kamis, 19 Juni 2008
Revolusi Seks Kaum Muda
 Dimuat di Harian SUARA MERDEKA, 19 Juni 2008
Dimuat di Harian SUARA MERDEKA, 19 Juni 2008Revolusi Seks Kaum Muda
Oleh: Edy Firmansyah
Tidak semua revolusi berjalan melalui demonstrasi-demonstrasi yang cenderung berjalan anarkis dan penuh kekerasan. Ada revolusi paling radikal yang bisa berlangsung dengan cara yang paling damai, nyaman, tapi memiliki daya perusak yang tak kalah dasyatnya. Revolusi itu adalah revolusi sex.
Ia tidak lahir melalui indokrinasi kaku, pamplet, propaganda, agitasi, orasi dan semacamnya. Melainkan lewat tehnologi, VCD, DVD, handycam, camera digital dan telepon seluler. Lihat saja, bagaimana publik seakan dibuat ternganga dengan berbagai fenomena yang lahir di kalangan kaum muda belakangan ini. Indonesia telah sampai pada sebuah era di mana produksi tayangan pornografi menempatkan para pemuda sebagai aktor utamanya. Rekaman adegan panas dan mesum ala pelajar kini dapat "dinikmati" dalam berbagai format seperti VCD, DVD atau telepon seluler.
 lemahnya peran pendidikan. Dalam skala nasional bernama sekolah itu tak dapat mengklaim mampu memberikan daya tahan ekonomi, daya tahan moral bahkan daya tahan nalar sekalipun pada bangsa ini (winarno Surachmad, Kompas 03/02/2000). Sekolah, tepatnya pengajar masih sering menggunakan sistem pengajaran gaya bank; Yakni siswa dianggap tidak bisa apa-apa dan guru sebagai satu-satunya sumber yang mencekoki siswa. Sehingga siswa lebih banyak diam (pola hamba-tuan). Siswa tidak dibantu menjadi kritis dan berpendapat secara bebas menggunakan kemampuannya.
lemahnya peran pendidikan. Dalam skala nasional bernama sekolah itu tak dapat mengklaim mampu memberikan daya tahan ekonomi, daya tahan moral bahkan daya tahan nalar sekalipun pada bangsa ini (winarno Surachmad, Kompas 03/02/2000). Sekolah, tepatnya pengajar masih sering menggunakan sistem pengajaran gaya bank; Yakni siswa dianggap tidak bisa apa-apa dan guru sebagai satu-satunya sumber yang mencekoki siswa. Sehingga siswa lebih banyak diam (pola hamba-tuan). Siswa tidak dibantu menjadi kritis dan berpendapat secara bebas menggunakan kemampuannya.  Sementara itu kalangan industri justru semakin memperkeruh suasana dengan menformat seks dalam bentuk hedonisme yang muncul dengan berbagai versi. Dalam majalah dan Koran muncul kisah-kisah tante girang, oom senang, gigolo, pereks, ayam kampus dan semacamnya. Sedangkan dalam film, misalnya munculnya film “Virgin”, “ML”, yang merupakan keberanian orang-orang film dalam mengesploitasi sex habis-habisan. Internet juga tak mau ketinggalan memberikan peluang bagi kaum muda mengakses dan menggunduh situs-situs porno.
Sementara itu kalangan industri justru semakin memperkeruh suasana dengan menformat seks dalam bentuk hedonisme yang muncul dengan berbagai versi. Dalam majalah dan Koran muncul kisah-kisah tante girang, oom senang, gigolo, pereks, ayam kampus dan semacamnya. Sedangkan dalam film, misalnya munculnya film “Virgin”, “ML”, yang merupakan keberanian orang-orang film dalam mengesploitasi sex habis-habisan. Internet juga tak mau ketinggalan memberikan peluang bagi kaum muda mengakses dan menggunduh situs-situs porno.  tentang seks. Misalnya di tengah maraknya seminar mengenai seks bebas, kaum remaja justru dikejutkan dengan adegan ranjang anggota dewan yang tersiar lewat media massa. Misalnya terkuaknya skandal seks Maria eva dan Yahya Zaini, serta adegan mesum Max Moein. Kita dapat berspekulasi bahwa fenomena semacam itu dapat memicu dorongan seksual yang tidak terkendali. Penelitian-penelitian menunjukkan perilaku sex di luar nikah terjadi karena dorongan dari luar seperti tayangan TV dan keseringan nonton BF.
tentang seks. Misalnya di tengah maraknya seminar mengenai seks bebas, kaum remaja justru dikejutkan dengan adegan ranjang anggota dewan yang tersiar lewat media massa. Misalnya terkuaknya skandal seks Maria eva dan Yahya Zaini, serta adegan mesum Max Moein. Kita dapat berspekulasi bahwa fenomena semacam itu dapat memicu dorongan seksual yang tidak terkendali. Penelitian-penelitian menunjukkan perilaku sex di luar nikah terjadi karena dorongan dari luar seperti tayangan TV dan keseringan nonton BF. TENTANG PENULIS
**Edy Firmansyah adalah Peneliti pada IRSOD (Institute of Reaseach Social Politic and Democracy). Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.
Minggu, 08 Juni 2008
Menuju Sastra Nobel
Dimuat di Harian SUARA KARYA, Sabtu 07 Juni 2008
Oleh: Edy Firmansyah Sejak Pramodya Ananta Toer meninggal 30 April 2006 silam, kegalauan banyak sastrawan negeri ini hingga sekarang adalah belum adanya sastrawan Indonesia yang menerima hadiah nobel. Meski setiap tahun ada ratusan sastrawan dari seluruh dunia yang diunggulkan mendapatkan Nobel untuk Sastra—meski akhirnya yang terpilih hanya satu orang—tetapi tak satupun sastrawan Indonesia yang disebut-sebut sebagai calon kandidat.
Sejak Pramodya Ananta Toer meninggal 30 April 2006 silam, kegalauan banyak sastrawan negeri ini hingga sekarang adalah belum adanya sastrawan Indonesia yang menerima hadiah nobel. Meski setiap tahun ada ratusan sastrawan dari seluruh dunia yang diunggulkan mendapatkan Nobel untuk Sastra—meski akhirnya yang terpilih hanya satu orang—tetapi tak satupun sastrawan Indonesia yang disebut-sebut sebagai calon kandidat.  Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kebudayaan Indonesia yang unik itu dimarjinalkan. Para sastrawan dan budayawan justru lebih memilih budaya eropa sebagai bahan dasar kesusastraan Indonesia. Sastra Indonesia diarahkan untuk publik kelas menengah. Jika ditarik ke belakang akar dari itu semua adalah pengaruh politik kolonial yang berhasil menumpas tumbuhnya kesusastraan nasional yang berbicara tentang kemerdekaan bangsa pada saat itu. Sebagai gantinya, ditumbuhkan kesusastraan berorientasi barat, yang menghembuskan keuniversalan nilai-nilai sastra, sehingga sastra alpa untuk berbicara tentang kemerdekaan dan pembebasan. Pada saat itulah muncul sastra Angkatan Balai Pustaka, yang merupakan cikal bakal kesusastraan Indonesia modern yang sekarang (Arif Budiman, 1985;104)
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kebudayaan Indonesia yang unik itu dimarjinalkan. Para sastrawan dan budayawan justru lebih memilih budaya eropa sebagai bahan dasar kesusastraan Indonesia. Sastra Indonesia diarahkan untuk publik kelas menengah. Jika ditarik ke belakang akar dari itu semua adalah pengaruh politik kolonial yang berhasil menumpas tumbuhnya kesusastraan nasional yang berbicara tentang kemerdekaan bangsa pada saat itu. Sebagai gantinya, ditumbuhkan kesusastraan berorientasi barat, yang menghembuskan keuniversalan nilai-nilai sastra, sehingga sastra alpa untuk berbicara tentang kemerdekaan dan pembebasan. Pada saat itulah muncul sastra Angkatan Balai Pustaka, yang merupakan cikal bakal kesusastraan Indonesia modern yang sekarang (Arif Budiman, 1985;104) sastra. Yakni sastra yang hanya mengagung-agungkan kelas atas atau kasta satria, sedang klas-klas atau kasta-kasta dibawahnya tidak punya peran sama sekali. Dalam pidato tertulisnya saat menerima penghargaan Magsaysay, di Manila, Pram mengatakan bahwa sastra yang dilahirkan dalam pangkuan kekuasaan dan berfungsi memangku kekuasaan semacam itu, langsung menggiring pembaca pada sastra hiburan, memberikan umpan pada impian-impian naluri purba pada pembacanya. Sejalan dengan Machiavelli, sastra demikian menjadi bagian alat tak langsung kekuasaan agar masyarakat tak punya perhatian pada kekuasaan negara. Singkatnya, agar masyarakat tidak berpolitik, tidak mengindahkan politik. Sastra dari kelompok kedua ini membawa pembacanya berhenti di tempat. Dan Pram memilih untuk tidak berpihak pada sastra seamcam itu.
sastra. Yakni sastra yang hanya mengagung-agungkan kelas atas atau kasta satria, sedang klas-klas atau kasta-kasta dibawahnya tidak punya peran sama sekali. Dalam pidato tertulisnya saat menerima penghargaan Magsaysay, di Manila, Pram mengatakan bahwa sastra yang dilahirkan dalam pangkuan kekuasaan dan berfungsi memangku kekuasaan semacam itu, langsung menggiring pembaca pada sastra hiburan, memberikan umpan pada impian-impian naluri purba pada pembacanya. Sejalan dengan Machiavelli, sastra demikian menjadi bagian alat tak langsung kekuasaan agar masyarakat tak punya perhatian pada kekuasaan negara. Singkatnya, agar masyarakat tidak berpolitik, tidak mengindahkan politik. Sastra dari kelompok kedua ini membawa pembacanya berhenti di tempat. Dan Pram memilih untuk tidak berpihak pada sastra seamcam itu.
**Tentang PENULIS
Edy Firmansyah Adalah Esais. Pengelola SBK (Sanggar Bermain Kata). Alumnus Universitas Jember.
Rabu, 04 Juni 2008
Hasrat Parpol dan Akseptabilitas Publik
Hasrat Parpol & Akseptabilitas Publik
Oleh Edy Firmansyah

Akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan dari 64 partai politik (parpol) yang mengembalikan berkas pendaftaran calon peserta Pemilihan Umum (pemilu) 2009, 13 di antaranya tidak lolos verifikasi administrasi. Ini artinya sebanyak 35 parpol boleh mengikuti tahap selanjutnya, yakni verifikasi faktual. Sedangkan 16 parpol yang memiliki kursi di DPR langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu.
Keputusan tersebut tentu saja membuat kecewa 13 parpol yang tidak lolos administrasi sebagai calon peserta pemilu 2009. Bahkan tak sedikit dari parpol yang tidak lolos menganggap proses verifikasi yang dilakukan KPU cacat dan tidak fair (Kompas, 1/6/08).
Kekecewaan itu memang dapat dimaklumi. Sudah banyak dana, waktu dan pikiran yang dikeluarkan partai-partai yang tidak lolos itu. Tapi apa boleh buat, kebebasan bersyarat —mendirikan partai—selalu mengandung konsekuensi; lolos atau tidak lolos. Dengan kata lain, kebebasan berpolitik bukanlah kekebebasan dalam pengertian yang filosofis.
Namun tulisan ini tidak akan terlalu jauh membahas mengenai kekecewaan parpol yang tidak lolos itu. Tulisan ini justru hendak menganalisa mengapa begitu banyaknya partai politik yang hendak terlibat menjadi peserta pemilu 2009? Meski bukan keputusan yang diambil KPU bukanlah keputusan final, lolosnya 51 parpol setidaknya menjadi isyarat mengenai hal itu. Apakah ini semakin menunjukkan betapa demokrasi semakin dimaknai secara obyektif dan cerdas oleh sebagian masyarakat, ataukah fenomena itu hanyalah bentuk dari ambisi politik kaum elite dan politisi busuk untuk terus menancapkan kuku kekuasaannya di negeri ini?
Peluang Demokrasi Sulit untuk memberikan jawaban pasti untuk pertanyaan itu. Tapi setidaknya banyaknya parpol yang hendak bertarung dalam pemilu 2009 semakin membuka mata kita bahwa masalah di negeri ini, mulai dari kemiskinan, pengangguran, korupsi, nepotisme dan pelanggaran HAM ternyata tak hanya melulu urusan sosial, budaya dan agama saja. Politik juga punya andil untuk mengatasi itu semua. Tapi seberapa besar peluang demokrasi untuk mengakhiri krisis di negeri ini?
Sulit untuk memberikan jawaban pasti untuk pertanyaan itu. Tapi setidaknya banyaknya parpol yang hendak bertarung dalam pemilu 2009 semakin membuka mata kita bahwa masalah di negeri ini, mulai dari kemiskinan, pengangguran, korupsi, nepotisme dan pelanggaran HAM ternyata tak hanya melulu urusan sosial, budaya dan agama saja. Politik juga punya andil untuk mengatasi itu semua. Tapi seberapa besar peluang demokrasi untuk mengakhiri krisis di negeri ini?
Ternyata dalam sejarahnya demokrasi selalu memiliki dua wajah. Cantik dan menyeramkan. Persis seperti judul sebuah film Beauty and The Beast. Cantik jika, demokrasi mampu menghasilkan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Penelitian Przeworski dan Limongi (1997) terhadap ratusan rezim otoriter dan demokratis selama tahun 1950-1990 menunjukkan ada keterkaitan erat antara kesejahteraan dan usia demokrasi. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan, semakin lama demokrasi bertahan.
Sebaliknya, demokrasi bisa sangat menyeramkan. Semenjak kemunculan pertama kali kira-kira lima abad sebelum tarikh Masehi dalam masa Yunani Antik di Kota Athena, demokrasi sudah menimbulkan banyak keraguan dari berbagai kalangan. Dan salah satu di antara pihak yang ragu —bahkan cenderung menolak— akan proses demokrasi adalah Socrates.
Parahnya lagi, di negara-negara dengan jumlah penduduk miskin banyak, tingkat pendidikan rendah, angka buta aksara tinggi, institusi sosial-politik lemah, demokrasi gampang dimanipulasi oleh elite-elite politik oportunis dan pemimpin despotik yang menawarkan janji-janji populis agar bisa terpilih sebagai wakil rakyat di parlemen atau pejabat pemerintahan. Namun, setelah terpilih terbukalah kedok aslinya. Bahwa tujuan para elite politik dan para pemimpin despotik itu merebut kekuasaan tak lain hanya untuk kepentingan pribadi (memperluas kekuasaan, mencari keuntungan ekonomi, menumpuk materi). Dengan tanpa rasa iba, mereka meninggalkan rakyat yang terus berkubang dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
Eskapisme Kemiskinan
Dengan kata lain, demokrasi tak ubahnya ”mesin pencetak uang” untuk membeli suara dalam
 pemilu sehingga proses manipulasi demokrasi berlangsung mengikuti kalender lima tahunan. Yang terjadi kemudian eskapisme kemiskinan yang berujung pada tindakan banal. Lihat saja, tindak kriminal, teror, penganiayaan, kekerasan dan konflik yang terus menjadi berita sehari-hari di negeri ini pemicu utamanya lebih disebabkan oleh kemiskinan. Dan itu akan terus berlangsung selama demokrasi belum mampu menghasilkan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan demokrasi bisa meregang nyawa.
pemilu sehingga proses manipulasi demokrasi berlangsung mengikuti kalender lima tahunan. Yang terjadi kemudian eskapisme kemiskinan yang berujung pada tindakan banal. Lihat saja, tindak kriminal, teror, penganiayaan, kekerasan dan konflik yang terus menjadi berita sehari-hari di negeri ini pemicu utamanya lebih disebabkan oleh kemiskinan. Dan itu akan terus berlangsung selama demokrasi belum mampu menghasilkan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan demokrasi bisa meregang nyawa. Tentang Penulis