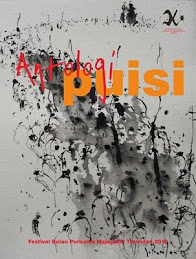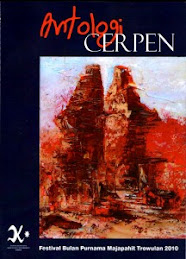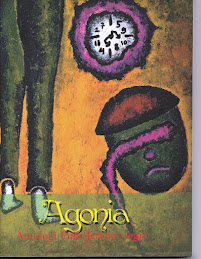DIMUAT DI HARIAN SURYA, 24 Juli 2008
Hentikan Kekerasan Pada Anak!
Oleh: Edy Firmansyah Wajah suram masih mewarnai peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli. Pasalnya, tindak kekerasan masih menjadi hantu bagi kehidupan anak-anak Indonesia. Dari waktu ke waktu Anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan terus berjatuhan.
Wajah suram masih mewarnai peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli. Pasalnya, tindak kekerasan masih menjadi hantu bagi kehidupan anak-anak Indonesia. Dari waktu ke waktu Anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan terus berjatuhan.
Berdasarkan data pada tahun 2004 terdapat 547 kasus kekerasan terhadap anak dengan rincian 221 kasus kekerasan seksual, 140 kekerasan fisik, 80 kekerasan psikis dan 106 kasus lain. Pada tahun 2005, jumlahnya meningkat lagi menjadi 766 kasus. Rinciannya, 327 kasus kekerasan seksual, 233 kekerasan fisik, 176 kekerasan psikis dan 130 kasus lain. Pada tahun 2006 kekerasan terhadap anak melonjak menjadi 1124 kasus kekerasan, dan 37 diantaranya berakhir dengan kematian. Sedangkan pada pertengahan tahun 2007 kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 1135 kasus dan 87 diantaranya berakhir dengan kematian.
Namun sebagaimana anomali sosial yang muncul di masyarakat, data diatas hanyalah puncak dari gunung es kekerasan tehadap anak. Artinya dari data tersebut, sebenarnya terdapat ribuan—atau bahkan lebih— kekerasan yang tak terungkap atau sengaja ditutupi. Sebab pelaku tindak kekerasan tersebut merupakan orang-orang terdekat dari para korban. Seperti misalnya, orang tua (ayah dan ibu), dan kerabat dekat (paman, bibi, kakek, nenek dan kakak). Bahkan menurut catatan Komnas Perlindungan Anak (PA) pelaku child abuse yang berasal dari orang terdekat mencapai 70 persen. Sisanya (30 persen) adalah orang yang tidak dikenal anak.
Menurut Terry E. Lawson, salah seorang psikiater internasional, setidaknya ada empat macam kekerasan terhadap anak (child abuse). Yakni, emotional abuse, verbal abuse, sexual abuse dan physical abuse (Benni Setiawan, 2008). Namun tulisan ini tidak akan membahas semua tidak kekerasan terhadap anak. Melainkan lebih memfokuskan pada physikal abuse, yakni tindakan menyakiti fisik anak. Pasalnya tindak kekerasan ini paling sering dilakukan orang-orang terdekat anak namun paling sering diabaikan masyarakat. Bahkan bisa dikatakan physical abuse belum pernah diatasi secara memuaskan.
belum pernah diatasi secara memuaskan.
Umumnya orang tua atau kerabat terdekat anak menganggap tindak pemukulan terhadap anak lazim dilakukan sebagai bentuk agak berlebihan orang tua dalam menjalankan ’hak’ mereka guna mendisiplinkan anak-anaknya (Pelzer, 2004). Masyarakat luas-pun kerap tidak terlalu mempermasalahkan physikal abuse selama tidak membuat kematian. Misalnya salah satu kasus yang sempat luput dari perhatian media lokal beberapa tahun lalu di salah satu pondok pesantren di Pamekasan, Madura, seorang kiai yang sengaja mencelupkan tangan seorang santri dalam air panas karena kedapatan mencuri kelapa masih dimaklumi masyarakat (termasuk orang tua santri) sebagai bentuk hukuman ’biasa.’ Berbeda misalnya ketika terjadi sexual abuse terhadap anak. Masyarakat bisa main hakim sendiri terhadap tersangka.
Kekerasan Dari Negara ke Keluarga
Permakluman masyarakat terhadap bentuk kekerasan fisik pada anak sebagai sebuah hukuman barangkali berangkat dari kekerasan struktural yang diciptakan raja-raja di Nusantara yang kemudian diadopsi oleh para penjajah (Belanda dan Jepang) dalam pendidikan. Kekerasan struktural itu dapat dirasakan pada kemunculan hegemoni bahasa, dimana hanya yang berkuasa yang berhak memberikan tafsiran atas realitas yang terjadi dalam masyarakat.
Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa menjadi hamba dalam lingkaran kerajaan dan ambtenaar (baca: pegawai) Belanda adalah idaman banyak masyarakat. Masuk dalam lingkaran istana (mesti jadi babu) atau pegawai (meski tukang sapu) dianggap kesuksesan. Padahal para hamba kerajaan dan ambtenar itu kerap mendapat perlakukan kasar dari atasan mereka. Namun perlakukan kasar tersebut dipelintir oleh kaum berkuasa kala itu sebagai bentuk pendidikan yang dapat menghantarkan hamba-hamba tersebut dalam puncak kesuksesan. Dalam masyarakat Madura ada lima manusia yang harus dipatuhi segala petuah dan diamini segala perbuatannya (meski berbau kekerasan), yakni Bapa’ Babu’ ghuruh, ratoh (Ayah, ibu, guru dan raja). Mereka dianggap kepanjangan tangan tuhan bahkan dapat menentukan nasib seseorang.
Nah, ketika korban kekerasan berhadapan dengan pelaku seperti orang tua atau guru kebanyakan dari mereka memilih berdiam diam, menyembunyikan masa lalu mereka tanpa mau berbuat apa-apa. ”Kalau membantah, takut kualat!” begitu kata para korban. Dengan kata lain mereka memilih agar kotak pandora kekerasan tertutup rapat.
Padahal dalam pandangan Freud, ahli psikologi analis, pengalaman traumatis yang dialami seseorang akan tersimpan jauh di alam bawah sadar seseorang dan dalam kondisi tertekan akan menciptakan prilaku menyimpang melebihi dari efek trauma yang pernah dialaminya. Film seperti; ”Hannibal the Rising,” ” The Mexico Chainsaw Beginning, ” hingga ”Ekskul” (yang diangkat dari kisah nyata) merupakan sedikit bukti bagaimana lingkaran kekerasan itu bergerak.
Agar Gerakan Anti Kekerasan Efektif Karena itu gerakan anti kekerasan terhadap anak yang digulirkan pemerintah tak akan berjalan efektif untuk memotong lingkaran kekerasan terhadap anak jika hanya berupa himbauan dan ajakan para orang-orang terdekat dan masyarakat agar lebih menyayangi anak-anak. Pemerintah haruslah yang pertama memberikan contoh untuk menghentikan tindak kekerasan dalam segala bentuknya. Bukankah negara yang kerap melakukan kekerasan pada masyarakat berupa; penggusuran, perampasan hak, hingga kekerasan pada demonstran lewat kekuatan koersifnya ?
Karena itu gerakan anti kekerasan terhadap anak yang digulirkan pemerintah tak akan berjalan efektif untuk memotong lingkaran kekerasan terhadap anak jika hanya berupa himbauan dan ajakan para orang-orang terdekat dan masyarakat agar lebih menyayangi anak-anak. Pemerintah haruslah yang pertama memberikan contoh untuk menghentikan tindak kekerasan dalam segala bentuknya. Bukankah negara yang kerap melakukan kekerasan pada masyarakat berupa; penggusuran, perampasan hak, hingga kekerasan pada demonstran lewat kekuatan koersifnya ?
Terakhir, penting membentuk sebuah lembaga khusus yang menangani tindak kekerasan di Indonesia yang anggotanya merupakan seleksi dari para psikolog terbaik Indonesia, seperti metode yang diterapkan Nanny 911 di Amerika yang terkenal itu. Selain untuk memberikan pendampingan khusus pada anak korban kekerasan juga mensosialisasikan secara intensif pada masyarakat bahwa kekerasan, apapun bentuknya adalah musuh kemanusiaan. Sebab selama kekerasan terhadap anak tidak ditangani secara serius di negeri ini, maka tinggallah api dalam sekam.
TENTANG PENULIS
**Edy Firmansyah adalah Peneliti pada IRSOD (Institute of Reaseach Social Politic and Democracy). Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.
WAKTU
JEJAK
- Artikel (93)
- Cerpen (20)
- Esai Budaya (31)
- Jendela Rumah (24)
- Kesehatan Masyarakat (5)
- Pendidikan (10)
- PUISI (71)
- Resensi Buku (25)
JEDA
Jumat, 25 Juli 2008
Hentikan Kekerasan Pada Anak!
Kamis, 24 Juli 2008
Menggugat Hak Pendidikan Anak
Dimuat di Harian JOGLOSEMAR, 23 Juli 2008
Menggugat Hak Pendidikan Anak  Ada kado istimewa menjelang peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang rutin diperingati tiap 23 Juli. Beberapa pelajar kembali mencatat prestasi emas dalam kompetisi pendidikan tingkat dunia. Indonesia yang diwakili tujuh pelajar SMP dan satu pelajar SD meraih lima mendali emas, dua perak dan satu perunggu di ajang Olimpiade Matematika 12th Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC) di Hongkong 12-16 Juli 2008 lalu. Sungguh prestasi yang patut diacungi jempol.
Ada kado istimewa menjelang peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang rutin diperingati tiap 23 Juli. Beberapa pelajar kembali mencatat prestasi emas dalam kompetisi pendidikan tingkat dunia. Indonesia yang diwakili tujuh pelajar SMP dan satu pelajar SD meraih lima mendali emas, dua perak dan satu perunggu di ajang Olimpiade Matematika 12th Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC) di Hongkong 12-16 Juli 2008 lalu. Sungguh prestasi yang patut diacungi jempol.
Dengan prestasi itu, Indonesia semakin membuka mata dunia bahwa kemampuan anak-anak Indonesia tidak bisa diremehkan. Anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang bisa diandalkan dan memiliki masa depan cerah. Buktinya, beberapa prestasi internasional dibidang pengetahuan berkali-kali pernah diraih.
Tapi apakah prestasi itu merupakan representasi dari seluruh anak-anak Indonesia? Apakah mutu pendidikan siswa Indonesia sudah mampu sejajar dengan negara maju? Nyatanya tidak. Dibanyak jurnal dan majalah pendidikan disebutkan bahwa mutu pendidikan Indonesia amat rendah, bahkan berada di rangking bawah dibandingkan dengan Negara Asia Tenggara. Hal tersebut karena, menurut Paul Suparno, Pakar Pendidikan dan Rektor Universitas Sanata Darma Yogyakarta, beberapa anak yang berhasil mendapatkan mendali emas dalam olimpiade science dunia adalah anak-anak genius. Maka dengan dibantu secara khusus lagi, mereka bisa menjadi sangat brilyan.(dalam Drost, 2005)  Sebab sebagian besar anak-anak Indonesia bukanlah anak-anak genius. Kebanyakan tidak semutu dan secerdas para peraih olimpiade itu. Penyebabnya? Tentu karena tidak meratanya fasilitas dan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu dan berfasilitas lengkap dengan tenaga pengajar yang professional terpusat di kota-kota besar. Yang lebih menyakitkan lagi, sekolah tersebut berbiaya mahal. Sehingga bisa ditebak yang dapat bersekolah di tempat tersebut adalah anak-anak dari kelas berpunya. Anak-anak dari keluarga pejabat, artis, pengusaha dan kelas atas lainnya.
Sebab sebagian besar anak-anak Indonesia bukanlah anak-anak genius. Kebanyakan tidak semutu dan secerdas para peraih olimpiade itu. Penyebabnya? Tentu karena tidak meratanya fasilitas dan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu dan berfasilitas lengkap dengan tenaga pengajar yang professional terpusat di kota-kota besar. Yang lebih menyakitkan lagi, sekolah tersebut berbiaya mahal. Sehingga bisa ditebak yang dapat bersekolah di tempat tersebut adalah anak-anak dari kelas berpunya. Anak-anak dari keluarga pejabat, artis, pengusaha dan kelas atas lainnya.
Disamping itu tak sedikit pula yang akhirnya harus tersingkir untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan. hanya gara-gara tidak bisa membayar biaya sekolah. Berdasarkan data Depertemen Pendidikan Nasional, sedikitnya 7,2 juta anak Indonesia tidak mampu merasakan bangku sekolah, terdiri dari 4,2 juta siswa SLTP dan 2,9 juta siswa SD dan SLTA.
Pendidikan Yang Mengebiri Imajinasi
Parahnya lagi, alih-alih mengembangkan potensi diri anak, mereka malah dimatikan kreatifitasnya dan potensi mengembangkan imajinasi. Sekolah masih saja menerapkan sistem gaya bank dalam mengajar; dimana guru menganggap dewa segala tahu, sementara siswa tidak tahu apa-apa. Akibatnya mereka hanya sekedar dicekoki pengetahuan. Bukan diarahkan untuk  mengembangkan potensi diri.
mengembangkan potensi diri.
Dengan kata lain anak-anak kita hanyalah kaum sub-altern yang sengaja dimatikan hak-haknya sebagai manusia. Mereka di cetak bukan menurut kemampuannya. Melainkan dicetak sesuai keinginan orang tua, sekolah dan masyarakat. Sehingga anak-anak Indonesia tak ubahnya ”beo-beo” yang dicetak secara khusus sebagai sekrup produksi.
Sebagai sebuah sekrup produksi yang dipentingkan bukan lagi kualitas pendidikan, melainkan sekedar kuantitas. Makanya jangan heran jika kini gelar akademik dijajakan secara bebas mirip pedagang kaki lima menjual vcd bajakan seharga Rp. 5.000 per keping. Bahkan—kalau mau jujur—hampir semua skripsi dan tesis sarjana kita adalah hasil plagiat. Jangan terkejut jika lulusan sarjana kita bukannya mencipta lapangan kerja, justru antre dalam deretan pengangguran dan pencari kerja. (Andreas Harefa, Menjadi Manusia Pembelajar, 2000)
Jika kondisi ini dibiarkan maka dalam waktu dekat kita akan kehilangan generasi penerus. Karena itu mengembalikan hak-hak anak adalah sebuah keniscayaan. Hak-hak anak yang dimaksud adalah hak menyatakan pendapat, hak mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mengembangkan potensi diri tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan adalah tugas pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak itu. Bukankah sudah termaktub dalam UUD dasar bahwa anak-anak dipelihara oleh Negara.
Karena itu kebijakan yang humanistik dan pro perkembangan anak penting untuk ditonjolkan. Misalnya sekolah yang membebaskan, yang tidak membedakan siswa berdasarkan kelas sosial. Artinya, anak-anak dari keluarga berpunya, dan anak-anak dari keluarga miskin dapat menikmati fasilitas pendidikan yang bagus dengan pengajar yang professional. Dengan kata lain, subsidi pendidikan bagi anak-anak miskin merupakan keharusan agar mereka mampu bersaing secara fair tanpa dibebani dengan masalah bayaran sekolah.
Bukankah banyak bukti bahwa ternyata anak-anak dari keluarga tak mampu yang berfaslitas seadanya justru bisa menyamai intelektual anak-anak dari keluarga berpunya? Novel “Laskar Pelangi” karya Andrea Hirata setidaknya bisa menjadi rujukan betapa ditengah kemiskinan yang mendera, tokoh seperti Lintang mampu mengembangkan kecerdasannya.
Dan hanya pemimpin yang peduli terhadap perkembangan dan masa depan anak Indonesia yang sanggup mewujudkan itu semua. Dengan pemimpin yang peduli pendidikan yang berpihak pada rakyat harapan besar kita agar anak-anak kita menjadi reinkarnasi Soekarno, Tan Malaka, Syahrir, Hatta, Soe Hok Gie baru yang mampu mengharumkan bangsa dan membawa negeri ini pada kemandirian tinggal selangkah lagi.
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Direktur People’e Education Care Institute (PECI) Surabaya. Peneliti pada IRSOD (Institute of Reaseach Social Politic and Democracy) Jakarta. Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.
Kamis, 17 Juli 2008
Ironisitas Pendidikan
Dimuat di Harian SUARA MERDEKA, 10 Juli 2008
Ironisitas Pendidikan  Sulit untuk menyangkal bahwa semua orang kini punya keyakinan yang seragam. Yakni, sekolah yang bermutu haruslah mahal. Mau bukti? Tiap musim Penerimaan Siswa Baru (PSB), yang selalu jadi rebutan orang tua siswa dan calon siswa adalah sekolah negeri unggulan atau favorit. Padahal biaya pendidikan di sekolah tersebut jauh dari kesan murah.
Sulit untuk menyangkal bahwa semua orang kini punya keyakinan yang seragam. Yakni, sekolah yang bermutu haruslah mahal. Mau bukti? Tiap musim Penerimaan Siswa Baru (PSB), yang selalu jadi rebutan orang tua siswa dan calon siswa adalah sekolah negeri unggulan atau favorit. Padahal biaya pendidikan di sekolah tersebut jauh dari kesan murah.
Di Solo misalnya, sejumlah sekolah negeri favorit memasang tarif tinggi dibalik kedok uang sumbangan sukarela orang tua siswa. Di jenjang SMU tarif masuk sekolah berkisar antara Rp. 12,5 – 15 juta, untuk SMP antara Rp. 7,5 – 10 juta dan SD sekitar Rp 1-3 juta. Di Tangerang dan Jakarta kondisinya sama. Untuk SD dan SMP dkenai sumbangan rata-rata Rp 1-2 juta. Bayaran tersebut belum ditambah dengan dengan uang buku dan seragam, dimana sekolah bekerja sama dengan berbagai perusahaan penerbit serta pedagang kain.
Memaksa masuk ke sekolah bermutu dengan biaya mahal semacam itu bagi kaum miskin justru menjadi petaka. Masih segar dalam ingatan kita kenekatan Ny. Junania Mercy warga Lowokwatu, Kota Malang. Hanya gara-gara tak sanggup lagi menanggung beban mahalnya biaya sekolah, yang mencapai Rp 1,6 juta per bulan, dia tega meracuni keempat putra-putrinya dengan racun potas. Kemudian bunuh diri. Belum lagi maraknya kasus bunuh diri pelajar hanya gara-gara tak mampu membayar biaya sekolah. 
Makanya jangan heran jika masih banyak anak-anak dari keluarga miskin tidak bisa bersekolah atau harus putus sekolah, hanya gara-gara tidak bisa membayar biaya sekolah. Berdasarkan data Depertemen Pendidikan Nasional, sedikitnya 7,2 juta anak Indonesia tidak mampu merasakan bangku sekolah, terdiri dari 4,2 juta siswa SLTP dan 2,9 juta siswa SD dan SLTA.
Sedangkan menurut Data dari pusat Informatika Balitbang Depdiknas menyatakan rata-rata angka putus sekolah SD (APS-SD) nasional sebesar 3,57% atau sekitar 940.438 siswa, rata-rata angka putus sekolah SLTP (APS-SLTP) ditingkat Nasional sebesar 7,66% atau 429.555 siswa. Ini artinya lebih besar dari APS-SD meski lebih kecil dalam kuantitas.
Sebenarnya pemerintah tidak tinggal diam dalam menyikapi fenomena tersebut. Di beberapa daerah sudah muncul inisiatif dari pemerintah untuk menekan biaya simbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah-sekolah negeri menjadi serendah mungkin. Bahkan ada yang mengratiskan SPP untuk sekolah negeri.
Namun kebijakan semacam itu belum menyentuh pada akar masalah kesulitan pendanaan pendidikan keluarga miskin. Di Jakarta, misalnya, meski sebagian besar warga miskin sudah mendengar tentang kebijakan pemerintah daerah yang menggratiskan SPP, namun mereka masih khawatir tidak bisa membiayai sekolah anak-anaknya. Maklum, meski SPP sudah digratiskan toh sekolah masih dapat menarik berbagai macam pungutan dari siswa. Mulai dari jual-beli seragam, buku pelajaran dan lainnya.
Dan kondisi diatas nampaknya akan menjadi fenomena tahunan dan akan terus terjadi selama pemerintah tidak segera mengambil langkah taktis mengatasi kesenjangan pendidikan. Salah satu yang layak dipertimbangkan adalah mengoptimalkan pendidikan bagi masyarakat pinggiran. Hal ini bisa terwujud jika pemerintah mau berkolaborasi dengan lembaga pendidikan terkait, semacam LSM untuk menggagas kembali pendidikan bagi masyarakat lokal. Misalnya dikembangkan pendidikan luar sekolah bagi masyarakat pinggiran, school without wall atau sekolah tanpa dinding bagi anak-anak miskin kota.
Setidaknya ada dua keuntungan jika pengarapan pendidikan bagi masyarakat pinggiran dan daerah pedalaman ini berjalan optimal. Pertama, semua anak-anak di daerah pinggiran tak akan ada lagi yang putus sekolah. Karena pendidikan model ini diupayakan nirbiaya. Kedua, masyarakat lokal tidak perlu takut kehilangan nilai budaya lokal sekaligus anak-anak tak akan kekurangan daya kreativitasnya. Karena model yang akan diterapkan dalam kurikulum ini adalah sistem pendidikan asli masyarakat.  Dalam system belajar asli, menurut Mohammad Zen, proses belajar seseorang mencakup empat hal yaitu; dalam belajar manusia akan mengalami sesuatu yang nyata, memikirkan secara konseptual, mengamati sesuatu sambil merenung dan mencobakannya dalam situasi lain yang lebih luas. Dengan memberikan pendidikan seperti itu, setidaknya akan membuat siswa tertarik karena berhubungan langsung dengan dunianya. Sekaligus juga akan mengikis pemikiran bahwa sekolah adalah memberi ijasah untuk diterima dalam dunia kerja, tetapi sekolah adalah tempat belajar hidup dan kehidupan.
Dalam system belajar asli, menurut Mohammad Zen, proses belajar seseorang mencakup empat hal yaitu; dalam belajar manusia akan mengalami sesuatu yang nyata, memikirkan secara konseptual, mengamati sesuatu sambil merenung dan mencobakannya dalam situasi lain yang lebih luas. Dengan memberikan pendidikan seperti itu, setidaknya akan membuat siswa tertarik karena berhubungan langsung dengan dunianya. Sekaligus juga akan mengikis pemikiran bahwa sekolah adalah memberi ijasah untuk diterima dalam dunia kerja, tetapi sekolah adalah tempat belajar hidup dan kehidupan.
Karenanya perlunya juga pelatihan intensif terhadap para pendidik, guru dan para pengajar di daerah mengenai metode pendidikan ini. Agar nantinya dapat mengembangkan pendidikan yang baik buat daerahnya masing-masing. Tak lupa pula untuk menaikkan gaji para “Oemar Bakri” agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarga, jadi tak hanya mencetak menteri, presiden dan para pejabat. Tetapi juga mampu hidup layak. Sebab salah satu indicator suksesnya pendidikan adalah tersedianya pengajar yang berkualitas.
Terakhir, perlu dibangunkan kesadaran moralitas para aparat pemerintah kita terutama dibidang pendidikan yang telah lama mati. Dengan sekali-sekali melihat kondisi di daerah terpencil atau mungkin hiduplah barang seminggu dua minggu dengan masyarakat setempat atau sesekali ikutlah menjadi pengajar untuk merasakan suka-duka jadi guru di desa. Dari situ dimungkinkan terbangun kesadaran bahwa apa yang dihadapi masyarakat pinggiran, penduduk desa lebih rumit dan kompleks, sehingga jiwa sosial aparatus pendidikan kita tergugah untuk menghentikan tindakan yang memiskinkan masyarakat seperti korupsi, penggusuran serta pencabutan subsidi pendidikan. Masalahnya adalah siapa yang akan memulai?
TENTANG PENULIS
**Edy Firmansyah adalah Peneliti pada IRSOD (Institute of Reaseach Social Politic and Democracy) Jakarta. Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.
Wajah OKP Islam dan Jalan Buntu Pembaruan
Dimuat di Radar Surabaya, 16 Juni 2008
Wajah OKP Islam dan Jalan Buntu Pembaruan
Oleh: Edy Firmansyah
Tapi apa lacur. Di negeri ini pembaruan pemikiran Islam justru ditafsirkan dengan penuh kecurigaan, bukan hanya dikalangan awam melainkan juga oleh kalangan terpelajar (baca: organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP)). Pembaharuan dianggap sebagai penafsiran-penafsiran baru yang menyimpang, bertentangan atau setidak-tidaknya berbeda dalam ekspresi dan artikulasi terhadap formulasi teologi atau fiqh tradisional yang sudah mapan.
Benar memang anggota OKP tak ketinggalan dalam mengikuti pemikiran tentang agama melalui bacaan, tetapi mereka tak mau ribet untuk berkutat dalam pembaharuan pemikiran. Cukuplah buku yang dibaca berakhir dengan diskusi di warung kopi. Bahkan jika terjadi perdebatan, yang paling sering dipermasalahkan hanya soal-soal yang furukiyah, yang tidak bertentangan dengan akidah. Di samping itu mereka lebih suka duduk berlama-lama di masjid, aktif dalam kegiatan ’ramadhan in campus’ yang tak lebih hanya bersifat ceremonial belaka daripada bergulat dengan pembaruan dan perubahan radikal.
Parahnya lagi, tak sedikit pemuda yang bergabung dalam OKP Islam hanya untuk bergaya, menaikkan prestise di kalangan mahasiswa, atau sekedar mencari pasangan hidup. Sehingga OKP tak jauh beda dengan biro jodoh. Inilah yang disesalkan Syakib Arsalan, dalam bukunya yang masyhur Limadza Ta’akhral Muslimun Wa Taqaddama Ghairuhum bahwa kemunduran kaum muslim dikarenakan Islam telah dijumudkan oleh pemiliknya sendiri.(Abdurrahman, dalam Jalaluddin Rahmad, et.al, 2001).
Makanya tak heran ketika dihadapakan dengan konsep pembaruan Islam, sikap reaksionernya selalu dikedepankan dibandingkan sikap ilmiah kritisnya. Fenomena yang paling mencolok ketika buku Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan harian Ahmad Wahib terbit (tahun 1981). Reaksi keras dari kalangan OKP Islam, diantaranya; HMI, PMII, dan IMM bermunculan. Bahkan reaksi tersebut disikapi oleh MUI kala itu dengan memberi saran kepada pemerintah cq Menteri Agama agar ”mengambil kebijakan terhadap buku tersebut”. Tujuannya agar tidak merusak aqidah dan syariah.
Hal diatas sebenarnya hanya salah satu contoh dari banyak kasus mengenai sikap reaksioner yang ditunjukkan OKP Islam dalam menjawab pembaharuan Islam. Lahirnya Jaringan Islam Liberal (JIL) yang dimotori Ulil abshar Abdalla, terbitnya buku Tuhan, Ijinkan Aku jadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan, atau Islam Kiri-nya Eko Prasetyo juga mendapat perlakukan yang sama dari beberapa OKP Islam. Bahkan yang terbaru adalah pro kontra mengenai Ahmadiyah di Indonesia. Ketika ada elemen masyarakat yang kemudian memberi dukungan terhadap Ahamdiyah, ternyata disikapi dengan tindak kekerasan. Seakan-akan formulasi teologi atau fiqh tradisional Islam merupakan harga mati yang tidak bisa diubah lagi.
Membaca Sejarah
Padahal sikap mepertahankan status quo semacam itu berdampak negatif. Islam kerap menjadi bulan-bulanan peradaban. Dalam catatan sejarah sepanjang abad ke-19 Islam telah bertekuk lutut dibawah kemajuan teknologi (khususnya persenjataan dan organisasi) barat. Dengan semangat revolusi industri barat kemudian berdiri sebagai penguasa dunia.
Sedangkan Islam dipandang sebagai bagian dari ciri keterbelakangan manusia Timur. Bahkan dibawah kolonialisme Belanda Islam hanyalah dianggap sebagai kekuatan nonkreatif yang identik dengan keterbelakangan manusia Indonesia yang dungu dan kurang terdidik. Islam dianggap tak pernah menyentuh masalah riil masyarakat dan tak mampu merumuskan masalah secara tepat.(Th. Sumartana dalam Wahib, 2003;402-403)
Fakta yang dapat kita baca adalah keberhasilan Snouck Hurgronje, yang dengan pikiran cerdas-kejinya, berhasil menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia, yang dimulai dengan menaklukkan Aceh tanpa pertumpahan darah. Hal ini terjadi karena kaum muslim cenderung menolak pembaharuan dan lebih senang tenggelam dalam kejumudan.
Padahal pembaharuan sangat penting dalam memurnikan kembali berbagai pemikiran atau pemahaman manusia terhadap agama Islam, yang telah berada dalam kondisi ’genting’. Sehingga Islam benar-benar terwujudkan sebagai rahmatan lil alamin dan terasa pula kehadiran di tengah-tengah kehidupan masyarakat sesuai perkembangan zaman.
Karena itu saat ini yang diperlukan adalah lahirnya Wahib-Wahib baru yang mampu memberikan pencerahan dalam pemikiran Islam sehingga Al-Qur’an dapat dijadikan senjata untuk menganalisa kehidupan manusia secara ilmiah sehingga selubung penindasan, eksploitasi manusia dapat dibongkar. Dan tentu saja harapa nterbesar jatuh pada kaum muda sebagai pelopornya.
Bukan sebaliknya. Kaum muda Islam justru bersembunyi dalam tempurung OKP sembari menjilat kekuasaan tanpa pernah peduli terhadap konsep pencerahan dan pembebasan manusia dalam arti yang sejati.***
TENTANG PENULIS
*Edy Firmansyah adalah Peneliti pada IRSOD (Institute of Reasearch Social Politic and Democracy), Jakarta. Alumnus Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.