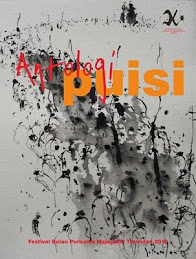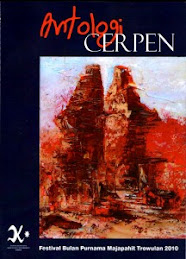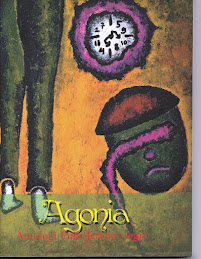Lagu Pengantar Tidur
pok ami ami
belaian kupu-kupu
siang jadi Nardi
kalo malam jadi Ayu
Ayu senyum manis
pada lelaki muda
adik jangan nangis
bapakmu masih kerja
WAKTU
JEJAK
- Artikel (93)
- Cerpen (20)
- Esai Budaya (31)
- Jendela Rumah (24)
- Kesehatan Masyarakat (5)
- Pendidikan (10)
- PUISI (71)
- Resensi Buku (25)
JEDA
Jumat, 28 September 2012
Lagu Pengantar Tidur
Rabu, 26 September 2012
Catatan Kecil tentang G 30 S di Madura (2)
Senin, 24 September 2012
Catatan Kecil Tentang G 30 S di Madura
Catatan Kecil Tentang G 30 S di Madura
“Dorr!”
Suara pistol revolver menggelegar memecah malam di kampung Patemon pada
medio Desember 1965. Orang-orang yang berteriak-teriak di depan rumah
Mbah Nisar sambil mengacung-acungkan clurit, golok, pentungan, dsb,
kontan terdiam.
”Pulang kalian semua! Disitu tak ada PKI. Kalau masih ngotot masuk ke
rumah Nisar, aku lobangi kepala kalian,” teriak kakek sambil
mengacungkan pistol ke orang yang berapa paling depan tepat di pagar
rumah Mbah Nisar.
Orang-orang kemudian membubarkan diri. Menjauhi Kakek. Maklum di
Patemon kakek terkenal cukup disegani. Sementara itu Nenek terus gemetar
di mulut gang sambil menenteng sampir-nya. Takut-takut gerombolan itu menyerang Kakek.
Sejak itu rumah Mbah Nisar tak pernah lagi disantroni orang. Nisar
adalah sahabat kakek. Bisa juga disebut saudara kakek karena dia diambil
anak oleh Paman kakek. Mbah Nisar, begitu aku memanggilnya, juga
seorang PNI aktif sama dengan kakek kala itu. Dan mungkin karena itulah
rumahnya disantroni gerombolan dan hendak dibunuh dengan tuduhan
bersekongkol dengan PKI.
Tapi rumah-rumah lain, ribuan rumah-rumah orang-orang PKI dan dituduh
PKI di Pamekasan, didobrak pintunya. Pemiliknya dihajar massa, lalu diseret ke dalam
truk. Dibawa ke daerah Blumbungan, Nyalaran dan tempat-tempat kuburan
missal lain di Kabupaten Pamekasan. Digebuki ramai-ramai. Tubuhnya
dicincang, ditembak, lalu mayatnya di kubur dalam lubang. Ditumpuk
dengan korban-korban lainnya.
Ratusan rumah juga dibakar. Perempuan di siksa, digorok lehernya,
tubuhnya dilarungkan ke sungai. Anak-anak terlantar, orang-orang gila
jadi pemandangan umum selain anyir darah dan bau busuk mayat-mayat yang
dibantai atas tuduhan; terlibat G 30 S kemudian dilelerkan begitu saja
di jalan-jalan seperti anjing kurap yang mati terlindas truk.
“Apakah orang PKI itu jahat?” aku memancing pertanyaan agar nenek
bercerita lebih banyak soal peristiwa seputar pembantaian orang-orang
PKI dan yang dituduh PKI pada tahun-tahun berdarah 1965-1966 di
Pamekasan-Madura.
”Aku tidak tahu.” Ujar nenek sambil memperbaiki letak tidurnya. Aku
yang sedari tadi tiduran di sampingnya, kontan bangun membantu perempuan
92 tahun yang melahirkan bapakku itu, mengangkat tubuhnya yang kini
ringkih karena usia terus menggerogotinya.
Ya. Memang tidak mudah mendapatkan informasi detail soal peristiwa
pembantaian anggota PKI dan yang dituduh PKI pada tragedi G30S di
Pamekasan-Madura. Selain karena ketakutan masyarakat atas stigma PKI itu
sendiri, juga karena masyarakat sudah termakan propaganda film G 30
S/PKI garapan Arifin C. Noer yang pada era Orde Baru wajib tonton setiap
tanggal 30 September malam. Dalam film tersebut digambarkan bahwa
anggota PKI dan semua organ yang berafiliasi dengannya adalah ‘keji.’
Membunuh 7 Jenderal AD dengan sadis. Pembunuhan dilakukan anggota
Gerwani (organ perempuan PKI) dengan menyilet dan memotong kemaluan
korban sambil menari telanjang dan pesta seks. Selain itu juga
merencanakan kudeta terhadap kekuasaan sah Soekarno dengan membentuk
Dewan Revolusi. Namun rencana itu dipatahkan Soeharto. Peristiwa dalam
film tersebut kemudian juga diabadikan dalam diorama Monumen Pancasila
Sakti di Lubang Buaya. Mungkin benar kata ungkapan; Kebohongan yang
diulang-ulang akhirnya bisa dianggap sebagai kebenaran.
Meski kakek saya seorang anggota PNI aktif, nenek saya perempuan
rumahan. Tak bisa baca tulis. Tak terlibat dengan organ perempuan sayap
PNI. Boleh dikata ‘benci’ politik. ”Karena kakekmu orang partai, uang
kerap habis hanya untuk membiayai kegiatan partai” keluhnya. Selain itu
kakek juga pengagum Soekarno, termasuk juga gayanya yang falmboyan dan
suka kawin.
Memang, rumah Nenek kerap jadi tempat kongkow orang-orang PNI pada
tahun 1960an. Berdiskusi siang-malam tentang segala hal. Dan nenek yang
menyiapkan semua kebutuhan makan orang-orang yang kadang bisa lebih dari
20 orang. Tapi nenek tak pernuh nguping. Lebih sibuk ngurusi anak atau
memasak di dapur.
Sementara kakek saya juga tak lagi bisa ditanyai. Dia meninggal pada
tahun 1967. Karena liver menurut diagnosa kedokteran. Tapi berdasarkan
cerita nenek dan bapak saya, kakek kena santet orang. ”Perutnya
membuncit. Tiap BAB selalu keluar darah disertai pasir hitam,” kenang
bapak saya yang pada waktu itu berusia 11 tahun.
Tapi ada satu peristiwa yang selalu nenek ingat. Pamannya, Riso ( aku
selalu memanggilnya Mbah Riso) pernah masuk penjara karena menjadi
anggota BTI (Barisan Tani Indonesia). Nenek saya yang rutin mengirimkan
makanan ke penjara selama Mbah Riso di penjara. Dan tiap kali ketemu
Mbah Riso di penjara kala itu, nenek saya selalu menangis. ”Wajahnya
selalu bengkak. Mungkin disiksa di dalam ( penjara, red). Tapi tiap
ditanya selalu bilang terjatuh di kamar mandi LP,” cerita nenek saya.
Penyiksaan dan pembunuhan dengan cara keji terhadap orang-orang PKI
dan yang dituduh PKI pada tahun 1966 memang sudah jadi rahasia umum.
Berdasarkan data dari John Rossa dalam bukunya “Dalih Pembunuhan Massal”
tercatat satu juta lebih orang mati dibantai. Malah Sarwo Edhie,
komandan operasi pembersihan orang PKI dalam sebuah wawancara, sesumbar
sudah menghabisi tiga juta orang PKI.
Tak lama memang Mbah Riso jadi tahanan karena dianggap ‘terlibat’ G
30 S yang pecah pada 1 oktober dini hari pada tahun 1965 itu. Sekitar 8
bulan. Itupun bisa keluar karena nyogok kepala penjara. Nenek tak ingat
berapa jumlahnya. Namun 8 bulan di penjara karena tuduhan PKI
menghancurkan nasib keturunannya kala Orde Baru berkuasa. Stigma turunan
Orde Baru; sekali bapak PKI anak cucu tetap PKI. Dan layak diberi
stempel; Berbahaya! Semua anak Mbah Riso tak satupun ada yg jadi pegawai
atau bekerja di perusahaan swasta. Semua anak laki-lakinya jadi sopir
angkot. Dua anak perempuannya Cuma jadi ibu rumah tangga dengan suami
yang bekerja srabutan. Pernah ada satu anak perempuan Mbah Riso yang
sempat jadi guru. Tapi setelah 2 tahun bekerja, tiba-tiba dia dipecat
dengan alasan yang tak jelas. Kemungkinan karena orang tuanya distigma
PKI. ”Padahal saya baru mendaftar jadi BTI. Enam bulanan. Dan tak pernah
aktif. Tapi rutin dapat jatah beras, gula, sabun, odol tiap bulan.”
Kenangnya ketika beberapa tahun lalu sebelum dia meninggal saya sempat
‘iseng’ bertanya soal keterlibatannya di BTI.
Mungkin ada benarnya pendapat yang mengatakan; ideologi seseorang
diuji ketika berada di masa-masa sulit. Pada masa sulit itu kita jadi
tahu siapa kawan seiring, siapa lawan. Siapa musuh dalam selimut. Siapa
kawan yang menikam dari belakang.
Menurut cerita nenek, ditangkapnya Mbah Riso karena laporan seseorang
yang tak lebih dari teman satu organisasinya sendiri. Mbah Tjikro. Dia
adalah anggota PKI. Cukup karib dengan Mbah Riso. Pada tahun 1966 itu
Mbah Tjikro juga ditangkap dan dipenjara. Lebih dulu dua bulan dari Mbah
Riso. Usut punya usut dari dialah segala daftar nama anggota ‘PKI’ di
kampung nenekku. Di dalam daftar itu ada nama Mbah Riso juga. Itulah
yang bikin Nenek kesal. Selain itu, Mbah Tjikro juga gak pernah cerita
kalau pembebasan tahanan bisa dilakukan dengan cara nyogok. Diapun bebas
dari penjara juga selain memberi daftar nama juga nyogok. ”Aku pernah
bertamu ke rumahnya. Tapi ketika ditanya dia nggak ngaku kalau keluar
penjara nyogok. Coba dia kasih tahu, Nom (Anom: Paman, Madura, red) Riso
bisa lekas dibebaskan. Meskipun uangnya dari utangan dan patungan antar
keluarga,” kenang nenek.
Selain peristiwa itu, Nenek tak ingat lagi hiruk pikuk dan jerit
pedih pada 1966 di Pamekasan, Madura. Nenek lebih banyak tinggal di
rumah, merawat kakek yang terkena Liver sampai dia meninggal pada awal
tahun 1967. Tapi sepanjang sakitnya, masih menurut cerita Nenek, Kakek
selalu menyelipkan pistol di bawah bantalnya. Pistol milik kantor. Sebab
pada masa itu pengawai bea cukai yang bekerja di pelabuhan memang
berhak memegang pistol.
Menurut cerita bapak saya, sejak terjadi tragedi 1966 itu, banyak
mayat-mayat bergelimpangan di sungai. Tangan terikat dengan tubuh tak
lengkap. Ada yang hilang kepalanya. Ada yang tebas dua belah tangannya.
Dan ada kepala yang ditancapkan di bambu lalu bambu tersebut di tanam di
pinggir perempatan jalan. ”Saya tak tahu siapa yang bunuh. Masih kecil
waktu itu. Tapi kerumunan orang selalu menyimpulkan satu hal tiap
menemukan mayat-mayat yang nyangkut di carang-carang pinggir sungai atau dileler di jalan-jalan; orang PKI.”
Bapak juga cerita pada tahun itu Ujian kenaikan kelas juga tertunda kurang lebih 8 bulan lamanya. Ada juga diberlakukan jam malam. Memang pembunuhan dan penculikan kerap dilakukan malam hari. Dari tindakan banal tersebut tak sedikit guru sekolah dan guru ngaji (ulama) yang juga masuk daftar orang PKI dan harus dihabisi.
Dan semua pembantaian keji dan berdarah-darah itu, yang dilakukan
militer dengan mendidik organ-organ paramiliter dan bekerjasama dengan
pemuda Anshor, hanya berdasar satu andaian yang sama sekali tak
terbukti; “Jika PKI menang, hal serupa juga akan dilakukannya”. Sebuah
pengandaian yang keji mengingat jutaan orang PKI mati dibabati seperti
hewan najis pada tahun 1965-1966. Tahun penuh darah. Tahun awal berdirinya orde baru. (bersambung)